LAFADZ DARI SEGI DILALAH (PENUNJUKAN) ATAS
HUKUM
pendapat Hanafiyyah dan Jumhur Ulama
(Syafi`iyah)
Oleh:
Maizul Imran, S.HI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ushuliyyah adalah Dalil syara’ yang bersifat menyeluruh, universal,
dan global (kulli dan mujmal). Jika objek bahasan ushul fiqih antara
lain adalah qaidah penggalian hukum dari sumbernya, dengan demikian yang
dimaksud dengan qaidah ushuliyyah adalah sejumlah peraturan untuk menggali
hukum. Qaidah ushuliyyah itu umumnya berkaitan dengan ketentuan dilalah lafadz
atau kebahasaan.
Sumber hukum dalam qaidah ushuliyah
adalah wahyu yang berupa bahasa, sementara qaidah ushuliyyah itu berkaitan
dengan bahasa. Dengan demikian
qaidah ushuliyyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang
terdapat dalam bahasa (wahyu) itu. Menguasai qaidah ushuliyyah dapat
mempermudah fakih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum
yang dihadapinya. Dalam hal ini Qaidah fiqhiyah pun berfungsi sama
dengan qaidah ushuliyyah, sehingga terkadang ada suatu qaidah yang dapat
disebut qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah.
Salah satu unsur penting yang digunakan
sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam adalah Ilmu Ushul Fiqh, yaitu
ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan
hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil
yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh akan diketahui nash-nash syara'
dan hukum-hukum yang ditunjukkannya.
Diantara kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang penting diketahui adalah
Istinbath hukum dari segi kebahasaan. Istinbath hukum dari segi kebahsaan sangat
penting, karena tidak mungkin bagi seorang faqih dapat mengambil suatu hukum
tanpa mengetahui ushlub bahasa dari bahasa (wahyu) yang akan diambilnya . Karena
bahasa (wahyu) yang ada dalam al-quran itu berbahasa arab, maka sudah tentu
bagi seorang ahli ushul atau faqih harus bisa memahami dan mengerti ushlub
bahasa tersebut.
Kita tahu bahwa nash-nash Al-Qur'an dan Sunah adalah dalam bahasa
Arab. Maka pemahaman hukum dari nash hanyalah menjadi satu pemahaman yang benar
apabila diperhatikan konotasi uslub dalam bahasa Arab dan cara-cara dilalahnya,
serta apa yang ditunjuki lafazh-lafazhnya, baik dalam bentuk mufrad maupun
murakkab (susunan). Oleh karena inilah, maka ulama ushul fiqh menaruh perhatian
serius pada penelitian tentang uslub Arab, susunan-nya, dan kata-kata
mufradnya, serta mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Di antara yang
ditetapkan oleh ulama bahasa ini ialah : Kaidah-kaidah
dan ketentuan-ketentuan (dhabith), yang dengan memperhatikannya dapat sampai
kepada pemahaman hukum dari nash-nash syar'iyyah dengan suatu pemahaman yang
benar, sesuai dengan apa yang difahami oleh bahasa Arab yang nash-nash tersebut
datang dengan bahasanya, dan juga menjadi sarana untuk memperjelas nash yang
mengandung kesamaran, menghilangkan kontradiksi yang kelihatan di antara
nash-nIash itu, dan mentakwilkan sesuatu yang menunjukkan untuk pentakwilannya,
serta lainnya yang berhubungan dengan pengambilan hukum dari berbagai nashnya.
Kaidah-kaidah dan dhabit-dhabit tersebut
adalah kebahasaan (lugha-wiyyah) yang diambil dari penelitian uslub
bahasa Arab, ia bukanlah suatu pembentukan keagamaan. la merupakan berbagai
kaidah untuk memahami susunan kalimat dengan suatu pemahaman yang benar. Maka memahami makna dan hukum daripadanya menempuh jalan bangsa
Arab dalam memahami susunan bahasa, mufradat dan uslubnya.
Pembahasan ini dibahas oleh Dr. Wahbah zuhaili dengan judul Dilalah
atau cara istinbath hukum dari nash-nash. Pemahaman
terhadap dilalah memiliki beberapa metode,
tergantung dari segi makna akan dipahami dilalah tersebut. Namun dalam pembahasan makalah
ini hanya yang berhubungan dengan penunjukan nash terhadap makna (دَلَالَةُ النَّصِ
عَلَى المَعْنَى) yang ada dalam lafadz nash. Dilalah nash terhadap makna pun
juga masih di bagi empat antara lain sebagai berikut :
1.
Dilihat dari segi bentuk lafadznya (‘am, khas, musytarok, muawwal)
2.
Dilihat dari segi penggunaan lafadznya (hakiki, majaz,
shorikh, kinayah)
3.
Dilihat dari segi tingkat kejelasan dan kesamaran lafadznya (tingkat
kejelasan : dhohir, nash, mufassar, muhakkam) dan ( tingkat kesamaran : khofi,
musykil, mujmal, mutasyabih)
4.
Dilihat dari segi cara penunjukkan suatu makna (maksud yang terkandung dalam
lafadz itu sendiri) (ibarat nash, isyarat nash, dilalah nash, iqtidlo’ nash)
Dari beberapa pembagian diatas, kita akan
terfokus kepada pembahasan yang ke empat yaitu dilalah nash terhadap makna
ditinjau dari cara penunjukkan suatu makna terhadap lafadz itu sendiri.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Urgensi Dilalah
dalam Ilmu Ushul Fiqh
Memahami dilalah dalam hal ini menjadi suatu
keharusan, mengingat nash syar'i atau perundang-undangan wajib diamalkan sesuai
dengan sesuatu yang dipahami dari ibaratnya (susunan kalimatnya), atau
isyaratnya, atau dilalahnya, atau juga iqtidha'nya. Karena segala sesuatu yang
dipahami dari nash dengan salah satu jalan dari empat jalan tersebut, maka ia
termasuk di antara madlul (yang ditunjuki) oleh nash, sedangkan nash adalah
hujjah atasnya, "Apabila pengertian yang dipahami dengan salah satu jalan
tersebut bertentangan dengan pengertian lainnya yang dipahami melalui jalan
dari jalan-jalan tersebut, maka makna yang dipahami dari ibarat dimenangkan
atas makna yang dipahami melalui isyarat; dan makna yang dipahami melalui salah
satu dari dua jalan tersebut dimenangkan atas makna yang dipahami melalui dilalah
".
Makna yang bersifat garis besar bagi kaidah ini ialah : Bahwasanya
nash syar'i terkadang menunjukkan beberapa makna yang beragam melalui cara dilalah
tersebut. Dilalah nash tersebut tidaklah terbatas pada makna yang dipahami
dari ibaratnya dan huruf-huruf-nya, akan tetapi terkadang pula ia menunjukkan
berbagai makna yang dipahami dari isyaratnya, dari dilalahnya, dan dari iqtidha'nya,
Setiap makna dari makna-maknanya yang dipahami dengan
salah satu dari cara-cara tersebut maka ia termasuk di antara madlul
(yang ditunjuki) oleh nash. Nash adalah dalil dan hujjah atas dirinya, dan ia
wajib mengamalkannya. Karena seseorang yang dibebani dengan nash (teks) juga
dibebani untuk melaksanakan makna yang ditunjuki oleh nash tersebut, dengan
salah satu cara yang diakui menurut bahasa. Apabila seorang mukallaf
mengamalkan madlul (yang ditunjuki) oleh nash dari sebagian cara dilalahnya
dan tidak mengabaikan pengamalan terhadap madlul nash dari cara yang
lain, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan nash dari sebagian segi. Oleh
karena itulah, maka para ahli ilmu ushul fiqh berkata : "Wajib mengamalkan
apa yang ditunjuki oleh ibarat nash dan apa yang ditunjuki oleh jiwa dan
penalaran nash tersebut”.
Untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang
terkandung dalam lafadz nash, baik secara harfiyah maupun secara maknawiyah
maka sebagai seorang faqih harus mengerti tata cara pemahaman lafadz itu, yaitu
dengan cara mempelajari konsep dilalah yang telah disusun oleh ulama ushuliyah.
Pembahasan tentang dilalah ini juga termasuk dalam salah
satu cara mempertajam sistem berpikir (ilmu logika).
Menurut Amir Syarifuddin , bahwa untuk mengetahui sesuatu tidak mesti melihat
atau mengamati sesuatu itu secara langsung tetapi cukup dengan menggunakan
petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut
dengan berpikir secara dilalah.[1]
B. Makna dilalah
Dilalah berasal Secara bahasa kata “دلالـة” adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kata
“دَلَّ- يَـدُلُّ” yang berarti menunjukkan dan kata dilalah
sendiri berarti petunjuk atau penunjukkan dilalah. Arti dilalah (الدلالة) secara umum adalah memahami
sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut مدلول (yang ditunjuk). Dalam hubungannya
dengan hukum, yang disebut madlul adalah hukum itu sendiri. Sedangkan
kata sesuatu yang disebutkan kedua disebut دليل (yang menjadi petunjuk). Dalam hubungannya
dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum.[2]
Sedangkan dilalah menurut istilah
adalah penunjukkan suatu lafadz nash kepada pengertian yang dapat dipahami,
sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari
sesuatu dalil nash. Tegasnya, dilalah lafadz itu ialah makna atau pengertian
yang ditunjukkan oleh suatu lafadz nash dan atas dasar pengertian tersebut kita
dapat mengetahui ketentuan hukum yang dikandung oleh sesuatu dalil nash.
Nash Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah merupakan
kumpulan lafadz-lafadz yang dalam ushul fiqh disebut pula dengan dalil dan
setiap dalil memiliki dilalah atau dilalah tersendiri. Yang
dimaksud dengan dalil di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab
Khalaf adalah sebagai berikut;
مـايـُسْـتَـدَ لُّ بِالـنَّـظْرِالصَّحِيْحِ فِـيْـهِ عَـلَى حُكْمِ شَـرْعِي
عَـمَلِي عَـلَى سَــبِـيْـلِ ا لـقَـطْعِ أَوِالـظَنِّ
Artinya; “segala sesuatu yang dapat dijadikan
petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan (menemukan)
hukum syara’ yang bersifat amali, baik sifatnya qoth’iy maupun zhanniy.”
Oleh karena itu dapat dipahami bahwa, pada
dasarnya, yang disebut dengan dalil atau dalil hukum itu ialah segala sesuatu
yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan
hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.
Sementara itu, yang dimaksud dengan dilalah,
seperti dijelaskan oleh Dr.wahbah Zuhaili dalam kitab ushulnya Dilalah adalah
:
كَـيْـفِـيَّةُ دَلَالَـةِ اللَّـفْــظِ عَـلَى الْمَـعْـنَى atau كَيْفِيَّةُ دَلَالَتِهِ عَلَى المُرَادِ المُتَكَلِّمِ
Yaitu; penunjukan suatu lafadz atas sesuatu
yang dimaksud oleh mutakallim atau cara penunjukkan lafaz atas sesuatu makna.
Dilalah sebenarnya merupakan salah satu bagian dalam
pembahasan ilmu logika, di mana untuk mengetahui sesuatu tidak mesti harus melihat atau mengamati
sesuatu itu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada.
Berpikir dengan menggunakan petunjuk atau isyarat disebut berpikir secara dilalah.
Oleh karena itu, dalam pembahasan ilmu Ushul al-Fiqh, dilalah adalah memahami
suatu hukum syar’i berdasarkan dalil hukum syar’i.[3]
C. Dilalah dalam Pandangan Ulama Hanafiyyah
Ulama Hanafiyah membagi dilalah kepada
dua macam, yaitu dilalah lafzhiyyah dan dilalah ghairu lafzhiyyah.[4]
1. Dilalah Lafzhiyyah (دلالة لفظية)
Dilalah lafzhiyyah adalah dilalah yang
menggunakan dalil menurut lahiriyahnya sebagai petunjuk hukum. Para fuqaha’
hanafiyyah membedakan empat tingkat makna dalam suatu urutan yang dimulai
dengan makna eksplisit atau makna langsung suatu nash. Urutan berikutnya adalah
makna yang tersirat yang diikuti oleh makna yang tersimpul dan terakhir oleh
makna yang dikehendaki. Adapun penjelasan keempat bagian tersebut secara
terperinci adalah sebagaimana berikut:
1) دلالة العبارة atau عبارة النص (makna eksplisit), yaitu makna yang
dapat segera dipahami dari shighatnya. Makna tersebut adalah yang dimaksudkan
dari susunan kalimatnya. Makna tersebut bisa langsung dipahami dari lafazh yang
disebutkan baik dalam bentuk penggunaan menurut asalnya (nash) atau bukan
menurut asalnya (zhahir).[5]
Pemahaman lafazh dalam bentuk ini adalah
menurut apa adanya yang dijelaskan dalam lafazh tersebut. Pemahamannya secara tersurat
(eksplisit) dalam lafazh. Contohnya dalam firman Allah QS. an-Nisa’ (4): 3.
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِيْ الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا
فَوَاحِدَةً
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja”
Dari ayat tersebut terdapat empat makna di
dalamnya. Pertama, legalitas pernikahan. Kedua, pembatasan poligami maksimal
empat. Ketiga, penetapan asas monogami jika poligami dikhawatirkan mendatangkan
ketidakadilan. Keempat, ketentuan bahwa wanita-wanita yatim harus diperlakukan
secara adil.[6]
Ciri ‘ibarah an-nash adalah bahwa ia membawa
ketentuan definitive (hukum qath’iy) dan tidak memerlukan dalil pendukung.
Tetapi jika nash tersebut dikemukakan dengan terma-terma umum, maka ia bisa
terkena kualifikasi. Dalam kasus demikian, ia tidak menjadi dalil qath’i
tetapi hanya dalil zhanni saja.
‘Ibarah an-nash bertingkat-tingkat kekuatannya sesuai
dengan kejelasan arti lafazhnya. ‘Ibarat dalam bentuk nash lebih kuat
penunjukannya dibanding dengan ‘ibarat dalam bentuk zhahir.[7]
2) دلالة الإشارة atau إشارة النص (makna tersirat), yaitu makna yang
tidak segera dapat dipahami dari lafazh-lafazhnya, tidak pula dimaksudkan
melalui susunannya. Akan tetapi ia adalah makna yang lazim bagi makna yang segera
dapat dipahami lafazhnya.[8]
Setiap lafazh menurut ‘ibaratnya memberi
petunjuk kepada maksud tertentu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafazh
tersebut. Para ulama ushul juga dapat menangkap bentuk lafazh yang demikian
untuk memberi petunjuk (isyarat) kepada maksud lain. Terkadang lafazh itu
memberi isyarat kepada lebih dari satu maksud di luar apa yang ditunjukkan oleh
‘ibaratnya (makna eksplisitnya). Contohnya dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233.
وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara ma’ruf…”
Makna eksplisit ayat tersebut adalah jelas
menentukan bahwa merupakan kewajiban ayah untuk menafkahi istrinya. Ungkapan المولود له yang berarti ayah sebagai pengganti
lafazh الأب yang digunakan oleh
Allah dalam ayat ini oleh para mujtahid menjadi titik perhatian. Dari lafazh المولود (yang dilahirkan/anak) dan له (untuknya) tersebut dapat dipahami
pula bahwa anak adalah kepunyaan ayahnya, atau dalam istilah hukum “anak itu
dinasabkan kepada ayahnya”.[9]
Dengan pemahaman tersebut terlihat bahwa ayat
tersebut yang menurut ‘ibaratnya mengandung maksud tertentu, juga menurut
isyaratnya menunjukkan kepada maksud yang lain.[10]
3) دلالة الدلالة atau دلالة النص (makna yang tersimpul), yaitu makna
yang dipahami dari jiwa dan penalaran nash. Jika ‘ibarat suatu nash menunjukkan
hukum suatu kasus dengan suatu ‘illat
yang menjadi dasar hukum tersebut, dan ditemukan kasus lain yang menyamai kasus
tersebut dalam segi ‘illat hukumnya atau bahkan ia lebih-lebih lagi, dan hal
itu dapat segera dipahami dengan semata-mata memahami bahasa bahasa, maka
secara bahasa dapat dipahami bahwa nash tersebut mencakup dua kasus tersebut,
dan hukum yang ditetapkan bagi manthuq (yang diucapkan) juga berlaku
bagi yang dipahami dengan ‘illat yang sama.[11]
Berbeda dari makna ‘ibarat dan isyarat, di
mana keduanya ditunjukkan dalam lingkup dan isyarat-isyarat nash, dilalah
an-nash tidak ditunjukkan dalam lingkup dan isyarat-isyaratnya. Di samping itu,
makna tersebut diperoleh melalui penarikan analogi yang diperoleh melalui
inferensi. Dilalah semacam ini sering disebut dengan istilah المفهوم الموافقة dan sebagian ulama menamakannya
dengan القياس الجلي.[12]
Dilalah an-nash ini terbagi menjadi dua,
yaitu:
1. Hukum yang akan diberlakukan kepada kasus
yang tidak disebutkan dalam nash keadaannya lebih kuat dibanding dengan kasus
yang terdapat dalam nash. Dilalah an-nash dalam bentuk ini disebut dengan المفهوم الأولوي (al-mafhum al-awlawiy) atau disebut pula فحوى الخطاب (fahwa al-khithab). Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Isra’ (17): 23.
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا
”Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan
kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka…”
‘Ibarah an-nash menunjukkan tidak bolehnya
mengucapkan kata-kata kasar dan menghardik orang tua. Hukum “tidak boleh”
itu juga berlaku pada perbuatan “memukul orang tua” secara lebih kuat,
karena sifat “menyakiti” yang menjadi alasan larangan pada pengucapan
kasar lebih kuat pada perbuatan “memukul”.
2. Hukum yang akan diberlakukan kepada kasus
yang tidak disebutkan dalam nash keadaannya sama dengan kasus yang disebutkan
dalam nash. Dilalah an-nash dalam bentuk ini disebut المفهوم المساوى (al-mafhum al-Musawi) atau لحن الخطاب (lahn al-khithab). Contohnya dalam
firman Allah: QS. An-Nisa’
(4): 10.
إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ
فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta
anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya…”
‘Ibarah an-nash dari ayat tersebut menunjukkan
tidak boleh memakan harta anak yatim secara tidak patut. Hukum “tidak boleh”
ini berlaku pula pada perbuatan yang sama dengan memakan harta anak yatim,
misalnya membakarnya atau memusnahkannya. Alasan yang terdapat dalam ayat
tersebut, yaitu “menghabiskan” harta anak yatim, terdapat pula pada perbuatan
membakarnya atau memusnahkannya yang sama kuatnya dengan perbuatan memakannya
secara tidak patut.[13]
4) دلالة الإقتضاء atau إقتضاء النص (makna yang dikehendaki), yaitu
makna yang ditunjukkan oleh suatu lafazh yang kebenarannya tergantung kepada makna
yang tidak disebutkan. Atau penunjukan lafazh kepada setiap sesuatu yang tidak
selaras maknanya tanpa memunculkannya.[14]
Dengan kata lain bahwa dalam suatu ucapan ada suatu makna yang sengaja tidak
disebutkan karena adanya anggapan bahwa orang akan mudah mengetahuinya, namun
dari susunan ucapan itu terasa ada yang kurang sehingga ucapan itu dirasakan
tidak benar kecuali jika makna yang tidak disebutkan itu dinyatakan. Contohnya
dalam firman Allah
QS. Yusuf (12): 82.
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْ أَقْبَلْنَا
فِيْهَا
“Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami
berada disitu, dan kafilah yang kami datang bersamanya…”
Menurut zhahir ungkapan ayat tersebut terasa
ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya kepada “negeri” yang bukan
makhluk hidup. Karenanya dirasakan perlu memunculkan suatu kata agar ungkapan
dalam ayat tersebut menjadi benar. Kata yang perlu dimunculkan adalah kata
“penduduk” sebelum kata “negeri” sehingga menjadi “penduduk negeri”, yang dapat
ditanyai dan memberi jawaban.
2. Dilalah Ghayru Lafzhiyyah (دلالة غير لفظية)
Dilalah ghayru lafzhiyyah adalah dilalah yang
menggunakan dalil bukan menurut lahiriyahnya sebagai petunjuk hukum. Dilalah
seperti ini disebut dengan دلالة السكوت (dilalah as-sukut) atau بيان الضرورة (bayan adl-dlarurah). Dilalah
semacam ini dibagi menjadi empat macam:[15]
1) Kelaziman yang untuk menyebutkan suatu
ketetapan hukum tertentu juga menetapkan hukum yang tidak disebutkan. Misalnya
dalam firman Allah
QS. An-nisa’ (4): 11.
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal
itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;”
Ketetapan bahwa bagian warisan ibu adalah
sepertiga, maka bagian ayah adalah dua pertiga ketika ahli waris hanya mereka
berdua karena bagian laki-laki adalah dua kali bagian wanita.
2) Penunjukan keadaan diamnya seseorang yang
berfungsi sebagai penjelasan persetujuannya.
3) Menganggap diamnya seseorang sebagai sudah
berbicara untuk menghindari adanya penipuan.
4) Penunjukan keadaan diam untuk sesuatu yang
berbilangan tetapi dihilangkan untuk menyederhanakan kata.
D. Dilalah dalam Pandangan Ulama Syafi’iyyah
Dalam pandangan ulama Syafi’iyyah, dilalah itu
dibagi menjadi dua macam, yaitu dilalah manthuq dan dilalah mafhum.[16]
Sedangkan penjelasannya adalah sebagaimana berikut:
1. Al-Manthuq (المنطوق)
Manthuq secara etimologi berarti sesuatu yang
diucapkan. Sedangkan menurut istilah ushul al-fiqh berarti penunjukan lafazh
terhadap hukum sesuatu yang disebutkan dalam pembicaraan (lafazh). Dari
definisi ini diketahui bahwa apabila suatu hukum dipahami secara langsung dari
lafazh yang tertulis maka cara seperti ini yang disebut pemahaman secara
manthuq. Dilalah al-manthuq ini terbagi menjadi dua:
1) Manthuq sharih yaitu makna yang secara
tegas yang ditunjukkan suatu lafazh sesuai dengan penciptaanya, baik secara
penuh atau berupa bagiannya. Misalnya, firman Allah dalam Surat an-Nisa’ (4): 3
yang mencantumkan hukum boleh kawin lebih dari satu orang dengan syarat adil,
jika tidak, maka wajib membatasi satu saja. Manthuq sharih ini dikenal dengan
istilah ‘ibarah an-nash dalam kalangan ulama Hanafiyyah.
2) Manthuq ghayru sharih yaitu pengertian yang
ditarik bukan dari makna asli suatu lafazh, tetapi sebagai konsekuensi dari
suatu ucapan. Dilalah ini terbagi lagi menjadi:
1. دلالة الإقتضاء atau إقتضاء النص, sebagaimana yang dipahami ulama
Hanafiyyah.
2. دلالة الإيماء, yaitu penyertaan sifat dalam hukum
sebagai ‘illat hukum yang mana jika sifat tersebut tidak menjadi ‘illat maka
penyertaan itu tidak ada artinya. Dengan demikian dilalah ima’ secara sederhana
dapat diartikan sebagai petunjuk yang mengisyaratkan sesuatu.
3. دلالة الإشارة atau إشارة النص, sebagaimana dipahami oleh ulama
Hanafiyyah, yaitu penunjukan yang tidak dimaksud oleh pembicara.[17]
2. Al-Mafhum (المفهوم)
Mafhum secara etimologi adalah sesuatu yang
dipahami dari suatu teks. Sedangkan pengertian mafhum menurut ulama ushul
adalah pengertian tersirat dari suatu lafazh atau pengertian kebalikan dari
pengertian lafazh yang diucapkan. Mafhum menurut mayoritas ulama ushul fiqh –
sebagaimana tergambar dalam definisi di atas – dapat dibagi menjadi dua macam:
1) المفهوم الموافقة yaitu mafhum yang lafazhnya
menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan
dalam lafazh. Mafhum ini terbagi menjadi dua, yaitu mafhum awlawiy dan mafhum
musawiy, sebagaimana keterangan dalam دلالة النص.[18]
2) المفهوم المخالفة yaitu mafhum yang lafazhnya
menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang
disebutkan. Atau bisa juga diartikan hukum yang berlaku berdasarkan mafhum itu
berlaku berlawanan dengan hukum yang berlaku pada manthuq. Mafhum mukhalafah
ini dinamai juga dengan dalil khithab. Mafhum mukhalafah ini terbagi dalam
beberapa bentuk, di antaranya adalah:
مفهوم الصفة .1 yaitu penunjukan suatu lafazh yang
terkait dengan suatu sifat terhadap kebalikan hukumnya ketika tidak ada sifat
tersebut. Contohnya dalam firman Allah QS. An-nisa’ (4): 25.
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
“Dan barang siapa di antara kamu (orang
merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu
miliki…”
Ayat ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki
mukmin boleh menikahi budak perempuan yang beriman ketika tidak mampu menikahi
perempuan beriman yang merdeka. Melalui mafhum mukhalafah diketahui haramnya
menikahi budak perempuan yang tidak beriman.
مفهوم الشرط .2 yaitu menetapkan kebalikan hukum
yang terkait dengan syarat ketika syarat itu tidak ada. Contohnya dalam firman
Allah QS. Ath-Thalaq
(65): 6.
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin…”
Ayat ini menegaskan adanya kewajiban suami
memberi nafkah terhadap istrinya yang telah dithalaq ba’in jika istri tersebut
dalam keadaan hamil. Secara mafhum mukhalafah suami tidak berkewajiban memberi
nafkah terhadap istrinya yang telah dicerai dalam keadaan tidak hamil.
مفهوم الغاية
.3
yaitu penunjukan suatu lafazh yang terkait padanya hukum yang dibatasi dengan
limit waktu atas tidak berlakunya hukum itu setelah limit waktunya berlalu.
Contohnya sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 187:
وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang
putih dari benang hitam, yaitu fajar…”
Ayat ini menjelaskan tentang bolehnya makan dan
minum pada malam bulan Ramadlan sampai terbit fajar. Secara mafhum mukhalafah
ayat ini dapat dipahami bahwa haram makan dan minum sesudah limit waktu habis,
yaitu setelah terbit fajar.
مفهوم العدد .4 yaitu penunjukan suatu lafazh yang
terkait padanya hukum dengan bilangan tertentu terhadap hukum kebalikannya
ketika bilangan itu tidak ada. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nur (24): 4.
وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita
yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,
maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera…”
Berdasarkan ayat ini, hukuman bagi orang yang
menuduh wanita baik-baik melakukan zina, sementara ia tidak mampu mendatangkan
empat orang saksi adalah, adalah didera sebanyak 80 kali. Dalam hal ini tidak
boleh mengurangi ataupun menambahi hukuman dera 80 kali.
مفهوم اللقب .5 yaitu meniadakan
berlakunya sebuah hukum yang terkait dengan suatu lafazh terhadap orang lain
dan menetapkan hukum itu berlaku untuk nama atau sebutan tersebut. Sebagaimana
terdapat dalam firman Allah QS. Yusuf (12): 4.
إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ
“(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada
ayahnya: “Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang,
matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.”
Dari ayat ini dipahami bahwa ucapan tersebut
hanya terkait dengan Nabi Yusuf karena tidak ada tidak ada kaitannya dengan
orang lain.[19]
E. Berhujjah dengan Menggunakan Mafhum
Mukhalafah
Para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan
mafhum mukhalafah sebagai hujjah. Kalangan Hanafiyyah tidak menerima mafhum
mukhalafah sebagai landasan pembentukan hukum. Di antara alasan yang
dikemukakan kelompok ini bahwa bila mafhum mukhalafah difungsikan pada banyak
ayat al-Qur’an dan hadits Nabi SAW, maka akan merusak pengertian yang terdapat
pada ayat dan hadits dan meniadakan hukum yang ditetapkan secara syara’ melalui
ayat dan hadits tersebut.[20]
Misalnya dalam firman Allah QS.
Ali Imran (3): 130.
يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan.”
Apabila digunakan mafhum mukhalafah terhadap
ayat ini maka riba yang tidak termasuk kategori berlipat ganda dihalalkan dan
dibolehkan oleh ayat ini. Pemahaman seperti ini jelas keliru karena riba yang
tidak berlipat ganda pun dilarang dan haram hukumnya. Ini menunjukkan bahwa
mafhum mukhalafah tidak dapat digunakan terhadap al-Qur’an.
Berbeda dengan kalangan Hanafiyyah, jumhur
ulama ushul al-fiqh menerima mafhum mukhalafah dengan mengecualikan mafhum
al-laqab sebagai hujjah. Mereka mengemukakan beberapa alasan, di antaranya:
1. Sahabat-sahabat besar, para tabi’in dan
imam-imam mujtahid menggunakan mafhum mukhalafah.
2. Secara logika adanya kaitan yang terdapat
pada nash-nash syariat dalam bentuk sifat, syarat atau ghayah bukan suatu
kesia-siaan, tetapi mempunyai manfaat tertentu. Di antara faidahnya
mengkhususkan hukum yang dimaksudkan oleh nash dan meniadakan selainnya.[21]
F. Syarat Berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah
Ulama yang memperbolehkan berhujjah dengan
mafhum mukhalafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakannya sebagai
hujjah. Syarat-syarat tersebut adalah:
1. Mafhum mukhalafah itu tidak bertentangan
dengan dalil manthuq atau mafhum muwafaqah, karena keduanya lebih kuat untuk
digunakan dalam istidlal.
2. Hukum yang tersebut dalam nash tidaklah
ditujukan sekedar merangsang keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu.
3. Hukum yang terdapat dalam nash tidak
merupakan jawaban atas pertanyaan yang menyangkut hukum khusus yang berlaku
waktu itu.
4. Dalil mantuqnya (yang tersurat) disebutkan
secara terpisah. Seandainya manthuq tidak terpisah dan disebutkan sebagai
rangkaian bagi dalil lain, maka tidak dapat diambil mafhum mukhalafahnya.
5. Manthuq bukanlah dalam bentuk hal-hal yang
biasa berlaku[22]
G. Analisis penulis.
Dari berbagai uraian diatas dan dari referensi
yang berkaitan dengan kajian ini, maka dapat dibuat sebuah peta konsep dari
pemikiran para ulama tentang penggunaan lafazd dari segi dilalahnya sebagai
berikut:
|
Golongan Hanafiyyah
(Zhahiriyyah, al-Ghazali, al-Amidi dari syafi`iyyah, Mu`tazilah)
|
Golongan Jumhur ulama
(Syafi`iyyah, Malikiyyah, Hanabilah)
|
|
1. Segi pembagian dilalah :
a. Dilalah Lafzhiyyah
1)
Ibarah nash
2)
Isyarah nash
3)
Dilalah nash
4)
Iqtidha` nash
b. Dilalah ghair lafzhiyyah disebut Dilalah
sukut/ bayan dharurah.
|
1. Segi pembagian dilalah:
a.
Dilalah Manthuq
a) Manthuq sharih
b) Manthuq ghair sharih
1.
Iqtidha`dan ima`
2.
Dilalah isyarah
b.
Mafhum
a)
Mafhum muwafaqah
1.
Aulawi
2.
Musawwi
b)
Mafhum mukhalafah
1.
Sifat
2.
Syarat
3.
Ghayah
4.
Adad
5.
Laqab
|
|
2.kesejalanan
secara maknawi
a. ibarah
nash = manthuq sharih
b. isyarah
nash = manthuq ghair sharih (dilalah isyarah)
c. dilalah
nash = mafhum muwafaqah
d. iqtidha`
nash = manthuq ghair sharih (iqtidha` dan ima`)
|
|
|
3. Menolak mafhum mukhalafah sebagai hujjah.
Alasan:
Bila mafhum
mukhalafah difungsikan pada banyak ayat al-Qur’an dan hadits Nabi SAW, maka
akan merusak pengertian yang terdapat pada ayat dan hadits dan meniadakan
hukum yang ditetapkan secara syara’ melalui ayat dan hadits tersebut.
|
3.menggunakan
mafhum mukhalafah dgn syarat-syarat tertentu.
Alasan ;
1. Sahabat-sahabat
besar, para tabi’in dan imam-imam mujtahid menggunakan mafhum mukhalafah.
2. Secara logika
adanya kaitan yang terdapat pada nash-nash syariat dalam bertuk shifat,
syarat atau ghayah bukan suatu kesia-siaan, tetapi mempunyai manfaat
tertentu. Di antara faidahnya mengkhususkan hukum yang dimaksudkan oleh nash
dan meniadakan selainnya.
|
|
4. Apabila terjadi pertentangan makna terhadap
dilalah-dilalah:
a. Dahulukan isyarat nash daripada dilalah
nash.
Alasan : bahwa Isyarah al-Nas merupakan unsur dari tata kalimat, sedangakan
dilalah al-Nas itu tidak diperoleh dari Mantuq Nas melainkan
dari Mafhum Nas, padahal makna yang diperoleh lewat Mantuq
lebih kuat bobot dilalahnya dari pada yang diperoleh lewat Mafhum.
|
a.
Dahulukan dilalah nash daripada isyarat nash.
Alasan : bahwa dilalah
Nas itu bersumber dari pemahaman kebahasaan terhadap Nash sehingga
ia lebih dekat kepada Ibarah al-Nas, sedangkan Isyarah al-Nas
diperoleh melalui pemahaman kebahasaan terhadap Nash.
|
|
5. Semua sepakat tidak beramal dengan mafhum
laqab
6. Semua sepakat tetang bolehnya berhujjah
dengan mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum ghayah, mafhum adad, diluar
lingkungan nash.
|
|
Dengan membandingkan pemikiran aliran
Hanafiyyah dan Mutakilimin di atas mengenai deskriktif dalalah al-Nas terhadap
hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Bagi aliran
Hanafiyyah terdapat empat dalalah, yaitu Ibarah al-Nas, Isyarah al-Nas, dalalah
al-Nas, dan Iqtida’ al-Nas.
b) Bagi aliran Mutakalimin, terdapat dua pokok
dalalah, yaitu dalalah Mantuq dan dalalah Mafhum
c) Apa yang
disebut sebagai ibarah al-Nas, Isyarah al-Nas, dan Iqtida’ al-Nas dalam
pemikiran aliran Hanafiyyah adalah secara maknawi tercakup oleh dalalah Mantuq
dalam pemikiran Mutakalimin.
d) Apa yang
disebut sebagai dalalah al-Nas dalam pemikiran aliran Hanafiyyah secara maknawi
sejalan dengan dalalah Mafhum Muwafaqah dalam pemikiran aliran Mutakalimin.
e) Dalam
pemikiran aliran Hanafiyyah tidak dikenal dengan dalalah Mafhum Mukhalafah
bahkan, mereka menolak dalalah ini sebagai hujjah Syar’iyyah.
Dapat
dikemukakan pula bahwa bahwa para ulama dari kedua aliran tersebut memiliki
titik kesepakatan dan titik perbedaan dalam pemikiran mereka tentang
konsep-konsep dalalah al-Nas. Dan titik kesepakatan mereka tersebut adalaha:
a) Ibarah Nas atau Mantuq Sarih merupakan
dalalah al-Nas yang peringkatnya yang paling kuat.
b) Mengiringi Ibarah al-Nas atau Mantuq Sarih
dalam hal kekuatan illat adalah secara berurutan, Isyarah al-Nas atau Mantuq
Ghairu Sarih, lalu dalalah Nas atau Mafhum Muwafaqah, lalu dalalah Iqtida’ atau
Mantuq Ghairu Sarih
c) Apabila terjadi pertentangan maknawi antara
dalalah-dalalah tersebut, yang harus diutamakan dan dipedomani adalah dalalah
yang peringkatnya lebih kuat.
Namun
dalam kasus pertentangan makanawi ini, aliran Mutakalimin lebih mengutamakan
dalalah al-Nas dari pada Isyarah al-Nas
ketika terjadi pertentangan maknawi tersebut, sedangkan aliran Hanafiyyah
sebaliknya lebih mengutamakan Isyarah al-Nas dari pada dalalah al-Nas.
Aliran
Hanafiyyah beragumentasi bahwa Isyarah al-Nas merupakan unsur dari tata
kalimat, sedangakan dalalah al-Nas itu tidak diperoleh dari Mantuq Nas
melainkan dari Mafhum Nas, padahal makna yang diperoleh lewat Mantuq lebih kuat
bobot dalalahnya dari pada yang diperoleh lewat Mafhum.
Aliran
Mutakalimin beragumentasi bahwa dalalah Nas itu bersumber dari pemahaman
kebahasaan terhadap Nas sehingga ia lebih dekat kepada Ibarah al-Nas, sedangkan
Isyarah al-Nas diperoleh melalui pemahaman kebahasaan terhadap Nas.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dilalah atau dilalah secara bahasa berarti petunjuk. Sedangkan
secara istilah ulama ushul al-Fiqh.
الدلالة هى مايدل
اللفظ من معنى
Artinya:
“Dilalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki
oleh lafazh.”
Dilalah lafzhiyah/الدلالة اللفظيه (penunjukan bentuk lafaz) yaitu dilalah
dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk
lafaz, suara atau kata. Dengan demikian, lafaz, suara dan kata, menujukkan
kepada maksud tertentu.
Dilalah ghairu lafzhiyah merupakan
dilalah yang ditunjukkan secara tidak jelas oleh lafazhnya. Hanafiyah membagi dilalah
ghairu lafzhiyah menjadi empat macam. Mereka menamakan dengan Bayan Dharurah
(penjelasan secara darurat). Keempat macam dilâlah itu memberi petunjuk dengan
cara sukut/diam.
B.
KRITIK DAN SARAN
Kami dari penulis, menyadari sepenuhnya bahwa
makalah kami ini jauh dari kesempurnaan, dan keterbatasan referensi untuk
itu kami berharap kepada pembaca,
terutama dosen pembimbing mata kuliah ini berupa kritik dan sarannya terhadap
makalah ini yang bersifat membangun.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
Moh. Shofiyul Huda MF, Ushul Fiqh: Pengertian, Sejarah dan Pemikiran
(Kediri: STAIN Press, 2009)
Fatihi al-Dariny, al-Manahij
al-Ushuliyyah fil Ijtihad bil Ra`yi (Damsyiq: Dar Kitab al-Hadits, 1975)
Imam Abd Aziz al-Bukhari, Kasyf
al-Asrar ala Ushul al-Bazdawi (Beirut: Mathba`ah Shina`i, t.th)
Muhammad Khudari Beik, Ushul Fiqh
(Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubra, 1969)
Abd Wahhab Khalaf, Ilm Ushul
al-Fiqh (Kuwait: Dar Qalam, 1972)
Zakiy al-Din Sya`ban, Ushul
al-Fiqh al-Islami (Damsyiq: Dar Kitab al-Hadits, 1958)
Muhammad Abu Zahrah, Ushul
al-Fiqh (Beirut: Dar Fikr al-Arabi, t.th)
Firdaus, Ushul Fiqh: Metode
Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2004)
Ibn Hazm, al-Ihkam fi Ushul
al-Ahkam (Beirut : Dar Afaq Jadidah, t.th)
Bacaan :
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh,
Jakarta: Amzah, 2011
Arifin,
Miftahul, Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam, cet. I,
Surabaya: Citra Media, 1997
Muhammad Hashim Kamali, Prinsip
dan Teori Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
Satria Effendi dan M. Zein, Ushul
Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008)
al-Amidi, Ihkam fi Ushul al-Ahkam.
Al-Ghazali, Mustashfa fi ilm Ushul.
Taj al-Din al-Subki, Jama` al-Jawami`.
Al-Syaukani, Irsyadul Fuhul.
Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh Islami.
(Maktabah Syamilah Raudhah file/program).
[3] Moh. Shofiyul
Huda MF, Ushul Fiqh: Pengertian, Sejarah dan Pemikiran (Kediri: STAIN
Press, 2009), h.102
[4] Fatihi al-Dariny, al-Manahij al-Ushuliyyah fil Ijtihad bil Ra`yi
(Damsyiq: Dar Kitab al-Hadits, 1975) h. 273
[5] Imam Abd Aziz al-Bukhari, Kasyf al-Asrar ala Ushul al-Bazdawi
(Beirut: Mathba`ah Shina`i, t.th) jilid 1, h. 67
[8] Fatihi al-Dariny, al-Manahij al-Ushuliyyah fil Ijtihad bil Ra`yi
(Damsyiq: Dar Kitab al-Hadits, 1975) h. 279
[9] Imam Abd Aziz al-Bukhari, Kasyf al-Asrar ala Ushul al-Bazdawi
(Beirut: Mathba`ah Shina`i, t.th) jilid 1, h. 70
[11] Fatihi al-Dariny, al-Manahij al-Ushuliyyah fil Ijtihad bil Ra`yi
(Damsyiq: Dar Kitab al-Hadits, 1975) h. 312
[16] Firdaus, Ushul
Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 170.
[21] Fatihi al-Dariny, al-Manahij al-Ushuliyyah fil Ijtihad bil Ra`yi
(Damsyiq: Dar Kitab al-Hadits, 1975) h. 392
[22] Fatihi al-Dariny, al-Manahij al-Ushuliyyah fil Ijtihad bil Ra`yi (Damsyiq:
Dar Kitab al-Hadits, 1975) h. 405
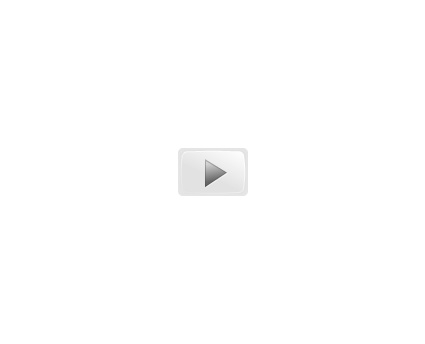
terimakasih banyak saya ucapkan kepada bapak yg menulis ini
BalasHapus