PENGUPAHAN DA`I PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh:
MAIZUL IMRAN, S.HI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia secara umum memilih hidup beragama
karena agama diyakini oleh mereka memiliki fungsi-fungsi yang membantu menjawab
kebutuhan asasi dari kehidupan mereka. Di
antara fungsi agama sebagaimana dirangkum oleh para pakar sosiologi
adalah fungsi edukatif, penyelamatan, pengawasan sosial, pemupuk persaudaraan,
dan fungsi transformatif.[1]
Fungsi edukatif agama adalah mengajarkan nilai-nilai otoritatif
tentang makna
dan tujuan hidup, mengenalkan manusia tentang Sang Pencipta, dan memberikan
ganjaran atau hukuman yang setimpal atas perbuatan baik dan buruk. Fungsi
penyelamatan artinya memberikan jaminan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
Fungsi pengawasan sosial agama adalah menjadi pengawal kaidah-kaidah susila
yang dipandang baik dan berkembang di masyarakat serta melakukan kritik terhadap
fenomena yang melanggar kaidah-kaidah susila. Agama disebut memiliki fungsi
pemupuk persaudaraan karena dianggap mampu mempersatukan sekian banyak
bangsa yang berbeda ras dan kebudayaan dalam satu keluarga besar di mana mereka
menemukan ketenteraman dan kedamain. Sedangkan disebut memiliki fungsi transformatif
karena diyakini dapat mengubah sebuah kondisi dari bentuk kehidupan masyarakat
lama menuju bentuk kehidupan baru.[2]
Mengingat besarnya fungsi agama Ibnu Khaldun (w.808 H) memandang bahwa
agama adalah salah satu pilar kekokohan suatu bangsa. Beliau mengatakan bahwa
sebuah negara akan menjadi kuat dan besar jika negara tersebut berbasis agama
atau selalu menyerukan nilai-nilai kebenaran.[3]
Senada dengan Ibnu Khaldun, Jean-Jacques Rousseau (w.1782 M) berpandangan bahwa pemerintahan
yang sehat dan kuat adalah pemerintahan yang dipimpin langsung oleh seorang
khalifah atau pemimpin politik yang sekaligus juga pemimpin agama sebagaimana
yang dipraktekkan
oleh Nabi Muhammad dan Khulafā’urrāshidīn.[4] Bangsa
Indonesia sejak lahirnya memiliki semangat keagamaan yang baik. Bukti
nyata dari kesadaran beragama itu tertuang dalam dokumen negara Indonesia, yaitu
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan tersebut dicantumkan
bahwa Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun redaksi yang dikenal sebagai
Piagam Jakarta di atas akhirnya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam
sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Ir. Sukarno
tanggal 18 Agustus 1945, penghapusan beberapa kata tersebut tidak mengurangi
arti pengamalan nilai-nilai agama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas
beragama Islam.[5]
Pemerintah Indonesia dalam konsep
kenegaraannya memandang bahwa pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi
salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut
agama dan keyakinan masingmasing. Selain
memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, pemerintah juga meyakini
bahwa agama mampu membendung kerusakan moral masyarakat. Pemerintah
Indonesia sangat menyadari akan adanya korelasi yang kuat antara kerusakan
moral yang terjadi saat ini dengan lemahnya komitmen untuk menerapkan nilai-nilai
agama.
Meskipun agama diyakini umatnya memiliki peran yang sangat
strategis, namun ia tidak dapat berfungsi dengan sendirinya manakala tidak
dikenalkan dan diajarkan oleh orang yang mengerti secara luas dan mendalam tentang
ajaran agama tersebut. Bahkan agama bisa berubah menjadi momok yang menakutkan
jika tidak dipahami secara baik, karena bisa berakibat pada pelegalan
pembunuhan dan perusakan atas nama agama.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Da`i dan Ruang Lingkupnya
Orang yang mengajak, mendorong dan memotivasi orang lain
berdasarkan baṣīrah (pemahaman yang luas dan mendalam) untuk meniti jalan Allah dan istikamah
di jalan-Nya serta berjuang bersama meninggikan agama Allah dalam terminologi
ilmu dakwah dinamakan dai.
Para dai dalam definisi di atas adalah para
ulama ‘āmilīn, mubalig,[6]
dan orang-orang yang bekerja di bidang agama yang bisa dijadikan uswah,[7]
yaitu ulama yang sekaligus berperan sebagai praktisi, bukan sekedar konseptor
atau orator. Dai dalam Islam mencakup semua kriteria di atas. Sepeninggal Rasulullah saw mereka dianggap
sebagai pengganti Rasul. Di tangan merekalah fungsi-fungsi agama di atas diembankan.
Rasulullah menyatakan bahwa para dai yang tampil menyuarakan nilainilai kebenaran
akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dai sangat
diharapkan memiliki ilmu keislaman yang mendalam karena materi yang akan mereka
sampaikan adalah tentang ajaran Islam. Selain itu, mereka juga diharuskan menguasai
ilmu-ilmu dakwah serta ilmu komunikasi yang memadai, karena ajaran
Islam yang mereka sampaikan bisa diterima dan berpengaruh pada audiens.
Di antara bentuk pengaruh strategis ilmu
komunikasi dalam kontribuasinya terhadap dakwah adalah: 1) Dapat mengubah
pendapat orang lain; Kekuatan mengubah pendapat orang lain disebut Nabi
Muhammad sebagai ‟sihir‟, karena bisa mengalihkan perhatian pendengar
kepada makna yang diinginkan oleh pembicara, meskipun keliru. 2) Menjadi faktor
yang menentukan baik buruknya manusia, karena pada saat melakukan komunikasi
kita hanya dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi.
3) Dapat mendatangkan kenyamanan psikologis bagi komunikator dan sekaligus
komunikan; 4) Jika diungkapkan dengan bahasa yang penuh optimistis, komunikasi
mampu membangkitkan semangat untuk melakukan perubahan.
Selain menyampaikan pesan, dai juga diharapkan mampu menjadikan
dirinya teladan
buat masyarakatnya. Tutur kata dan perilaku yang baik dari dai sangat potensial
ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Gabriel Tarde menyebut fenomena peniruan
sikap dan perilaku seseorang dengan istilah imitasi.[8] Paduan antara pesan yang
dikemas dengan baik dan perilaku yang dapat ditiru dan diteladani oleh
masyarakat membuat peran dai sangat strategis untuk melakukan perubahan,
meskipun pada akhirnya perubahan itu sendiri sangat tergantung dari tekad
komunikan untuk berubah.
Mengingat pentingnya agama bagi masyarakat, maka beramal di
lapangan dakwah
dan mengajarkan agama kepada masyarakat dalam pandangan Islam adalah pilihan
pekerjaan yang paling mulia.
Secara umum dai dapat dikelompokkan dalam
kategori pemimpin agama (religious leader).[9] Di
antara pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpin agama adalah: a) Melakukan
pelayanan ibadah dan menyelenggarakan upacara-upacara ritual, seperti
kelahiran, pernikahan, kematian; b) Menyelenggarakan pendidikan agama untuk
komunitas di mana mereka berada; c) Melakukan pertemuan-pertemuan kelompok; d)
Memberikan konseling kepada seseorang atau pasangan terkait dengan masalah spiritual,
emosional, dan kebutuhan-kebutuhan personal; e) Mengunjungi orang-orang di
penjara, rumah sakit, dan dari rumah ke rumah.
Bidang pekerjaan yang digeluti oleh para dai
sebagaimana disebutkan di atas dirasakan sangat membantu masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan sejalan dengan usaha pemerintah untuk
memenuhi salah satu hak dasar rakyat.
Kalau melihat agenda pembangunan nasional Indonesia, terutama dalam kebijakan
meningkatkan kualitas kehidupan beragama tahun 2004 hingga 2009, kita dapat
membaca bahwa pemerintah sebenarnya memahami peran dai untuk menyukseskan
agenda tersebut. Di antara arah kebijakan pemerintah tahun 2004-2009 dalam
upaya meningkatkan kualitas beragama adalah meningkatkan kualitas penyuluh
agama dan pelayanan keagamaan lainnya.
Dalam tataran kebijakan, langkah yang diambil pemerintah sudah
benar dan sangat strategis. Jika kebijakan ini diterapkan secara serius
dengan segala perangkat pendukungnya maka kegundahan pemerintah akan gejala negatif yang
berkembang di masyarakat seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan
narkoba, perjudian,
meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga, pornografi, dan
pornoaksi akan dapat diminimalisir.
Sayangnya, pekerjaan yang membawa dampak positif terhadap perubahan
ini belum
masuk dalam prioritas pekerjaan yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah,
tidak seperti guru atau dokter. Sedangkan di kalangan para ulama, mereka
sepakat bahwa dakwah adalah profesi paling mulia, tetapi mereka berselisih pendapat
tentang hukum boleh tidaknya dai mengambil upah dari profesinya itu.
Ide memasukkan kerja dakwah sebagai salah satu pekerjaan
dilontarkan oleh Ibnu Khaldun (w. 808 H). Dalam kitabnya al-Muqaddimah, saat
menyebutkantentang bentuk-bentuk profesi dan pekerjaan, salah satu profesi yang
beliau masukkan adalah ’al-qā’imīn biumūr
al-dīn (orang-orang yang bekerja di bidang agama). Yang dimaksud
oleh Ibnu Khaldun adalah kadi, mufti, guru agama, imam, khatib, muazin, dan
yang sejenisnya. Menurut beliau, orang yang bekerja di bidang ini secara umum aset
kekayaan mereka tidak besar. Sebabnya, menurut beliau, adalah karena tidak banyak
orang yang memiliki kepentingan langsung dengan pekerjaan ini. Mereka tidak
menganggap ruang lingkup pekerjaan dakwah sebagai kebutuhan dasar. Karena itu
tidak banyak yang merasa berkepentingan dengan mereka.[10] Ulama-ulama
sebelum Ibnu Khaldun sebenarnya, sudah memberikan isyarat di
dalam kitab-kitab mereka tentang adanya gejala sosial ini. Isyarat itu
setidaknya dapat dilihat dari kontroversi pendapat sekitar boleh tidaknya
dakwah dijadikan profesi sejak abad pertama Hijriyah. Mazhab empat, Imam Hanafi
(80-150 H), Imam Malik (93-179 H), Imam Syafii, (150- 204 H) dan Imam Hambali (164
-241 H) telah berbicara tentang masalah ini dalam konteks respons terhadap
pertanyaan boleh tidaknya mengambil upah dari berdakwah. Dalam kajian-kajian fiqh,
pekerjaan dan pengupahan dai dapat ditemukan dalam kajian tentang ijārah [11] dan jiʻālah.[12]
Di antara kitab-kitab Mazhab Hanafi yang
mengkaji masalah ini adalah Sharḥ Maʻāni al-Âtsār, karya Abu Ja‟far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah al-Azdi al-Ṭaḥāwi. Beliau memasukkan kajian pengupahan dai dalam kitab ijārah.[13] Ibnu Maudūd al-Mūṣili dalam kitab al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār juga memasukkan kajian ini dalam kitab ijārah.[14]
Sedangkan Mazhab Maliki seperti al-Mudawwanah
juga memasukkan kajian ini dalam kitab al-ju’lu wa al-ijārah.[15]
Mazhab Syafii juga demikian, memasukkan kajian ini dalam kitab al-ijārah. Sedangan kitab al-Mughni karya Ibnu
Qudāmah al- Ḥanbali memasukkannya dalam pasal al- jiʻālah.
Para ulama fiqh yang menjadi rujukan umat Islam secara umum
memiliki pendapat
yang beragam dalam menyikapi persoalan ini. Kitab fiqh Mazhab Hanafi, al-Ikhtiyār li Taʻlīl al-Mukhtār menyebutkan dua pendapat Mazhab Ḥanafi dalam hukum
menerima upah dari kerja dakwah. Para ulama mutaqaddimīn (terdahulu) berpendapat
tidak boleh menerima upah, sedangkan muta’akhkhirīn-nya mengatakan boleh.
Mazhab Maliki sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Mudawwanah,
ketika ditanya
tentang hukum mengontrak seseorang untuk menjadi muazin atau guru agama,
Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Imam al-Syafii
berpendapat bahwa muazin sebaiknya tidak dibayar, kecuali tidak menemukan
muazin yang sukarela melakukannya.[16]
Sedangkan Mazhab Hambali secara umum memandang bahwa muazin tidak boleh mengambil upah dari pekerjaannya
sebagai muazin.
Hingga hari ini di dalam masyarakat masih terjadi kontroversi hebat
seputar status
dai yang hidup dari aktivitas dakwah. Awal tahun 2001, majalah Saksi menurunkan
headline berjudul ‟Dai Matre‟, membahas adanya kecenderungan dai untuk
mencari hidup dari lahan kerja dakwah. Selanjutnya Majalah Harkat di
tahun yang
sama juga menurunkan headline yang berjudul “Menyingkap Gaya Hidup ParaUstadz‟,
isinya menunjukkan kontroversi seputar dai yang menghidupi dirinya dari kerja
dakwah.[17]
Sebuah situs berbahasa Arab yang bernama ‟Muntadayāt al-Shabakah al- Alma‘i‟ membuka rubrik diskusi bertemakan ‟Ṭalab al-Dunya bi al- Dîn’ (mencari dunia dengan agama). Ada lima tema sentral yang didiskusikan: pertama, mencari nafkah
dengan Alquran dalam bentuk menjadi imam, menghafal Alquran dalam rangka
untuk mendapatkan pekerjaan mengajarkan Alquran, atau mempelajari dan menghafal
Alquran agar mendapatkan perhatian pemerintah; kedua, membangun masjid
agar bisa diangkat menjadi imam, muazin, atau petugas masjid; ketiga, berceramah
dengan mendapatkan imbalan; keempat, bisnis barang-barang islami seperti
kaset murattal, dsb; kelima, berpenampilan beda dengan masyarakat atas nama
agama dengan mempertontonkan perilaku yang aneh-aneh. Peserta diskusi dengan
berbagai belakang masih terbelah dalam dua pendapat besar, antara setuju dan tidak
setuju. Kalangan yang menolak menganggap bahwa ceramah seharusnya tidak dijadikan
mata pencaharian. Mereka beralasan bahwa amplop dapat menyebabkan dai tidak
kritis, tidak independen, dan tidak berwibawa dalam dakwahnya. Bahkan dengan
metoda pemberian amplop seperti ini, yang menjadi raja adalah pihak pemilik kapital.
Jika tidak suka, maka dia memiliki hak penuh untuk tidak memakai dai tersebut,
padahal sangat mungkin apa yang dikatakan dai itu adalah benar. Kalau ini terjadi,
maka pesan dakwah tidak mungkin tersampaikan dengan utuh. Akibatnya, ada dai
yang dianggap tidak berani menyuarakan kebenaran secara gamblang karena khawatir
tidak diundang lagi.
Ketidakjelasan status hukum terhadap masalah ini berdampak kepada kurangnya
perhatian berbagai pihak terhadap kehidupan para dai. Sebagian mereka hidup
atas pemberian sukarela masyarakat di mana mereka beraktivitas. Mereka diminta
untuk mengajar di banyak tempat, kadang-kadang satu hari penuh melayani kebutuhan
masyarakat, pagi, siang, sore, dan malam. Di antara mereka ada yang pulang
dengan tangan kosong, ada yang pulang dengan membawa sekotak nasi, dan ada
juga yang membawa amplop.
Kesimpangsiuran pendapat tentang hukum mengambil upah ini juga menimbulkan
ketidakjelasan pendapatan dai. Budaya kontrak kerja, berapa lama mereka
akan menimba ilmu dari dai, berapa imbalan yang layak untuk mereka terima, belum
menjadi budaya masyarakat kita. Ada dai yang tidak mendapatkan imbalan materi
sama sekali, ada yang mendapatkan bayaran sangat rendah, ada yang mendapat
imbalan sedang dan ada pula yang mendapatkan imbalan sangat tinggi.
Akibat ketidakjelasan perjanjian di awal ini sering menimbulkan
penyakit hati.
Sebagian dai karena tidak puas menerima imbalan sedikit atau tidak diberi imbalan,
sedang di tempat lain dia pernah mendapatkan hasil yang lumayan, maka terjadilah
penolakan halus terhadap permintaan masyarakat yang tidak member imbalan
atau minim imbalannya, meskipun sebenarnya dia belum memiliki jadwal di tempat
yang lain. Sebaliknya, jika tawaran datang dari tempat yang cukup menjanjikan,
dia terima secara spontan meskipun harus mengorbankan janji yang telah
dibuat dengan pihak lain. Sebenarnya tidak layak dai bersikap seperti itu,
tetapi kasus
di lapangan sering terjadi. Dampak lain adalah penyebaran dai menjadi tidak merata,
banyak menumpuk di daerah perkotaan, sedangkan di desa mencari orang yang
bisa khutbah saja kesulitan. Di antara sebab tidak idealnya sebaran dai adalah kekhawatiran
mereka tidak dapat hidup layak jika terjun ke pedesaan, karena secara umum
pedesaan tidak menjanjikan pendapatan sebagaimana di kota.
Kondisi dai seperti ini akan mengancam gerak laju dakwah. Dakwah
yang bertujuan
untuk melakukan transformasi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya dari
kondisi tertentu menuju kondisi ideal memerlukan orang-orang profesional, inovatif,
dan mandiri. Sedangkan orang yang sibuk memikirkan kehidupan harian keluarganya
tidak akan produktif dalam kerja-kerjanya. Menurut Rasulullah Saw, kemiskinan
dan kefakiran membuat orang tidak bisa berfikir merancang masa depan. Beliau
menyebutnya dengan ’faqran munsiya’. Sedangkan pemerintah sampai hari ini belum menjadikan program ini
sebagai salah
satu program prioritas. Dari 224.778.700 penduduk Indonesia hari ini, jumlah penyuluh
agama fungsional yang diangkat oleh Kementerian Agama menurut data tahun
2007 berjumlah 4.086 orang. Artinya, satu penyuluh harus melayani sekitar 55.000
masyarakat. Penyuluh-penyuluh tersebut dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu
penyuluh fungsional, penyuluh terampil dan penyuluh profesional. Pembagian ini
berdasarkan kepada kepangkatan dan masa bakti masing-masing penyuluh di Kementerian
Agama.
Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini juga tampak dari
pemberian honorer terhadap penyuluh non PNS. Jumlah penyuluh yang dipilih dan
besaran honornya
masih sangat jauh dari harapan. Selain itu, pembinaan dan peningkatan kualitas
para dai dan penyuluh juga sangat jarang diselenggarakan.
Di sisi lain, beberapa kalangan melangkah sangat jauh dari tradisi
di atas. Mereka
bahkan terang-terangan memasang tarif jika diundang untuk ceramah atau mengajar
di tempat tertentu, meskipun biasanya melalui para manajernya. Kalangan ini
betul-betul mengelola dakwah dengan manajemen bisnis modern. Mereka dating menawarkan
program, menandatangani nota kesepahaman, dan akhirnya berlangsunglah
acara sesuai dengan kesepakatan.
Kalangan lain merasa risih dengan kevulgaran kelompok kedua dalam menetapkan
tarif. Mereka mengambil jalan tengah. Ketika membicarakan nota kesepahaman
dan sampai pada pembicaraan tarif, mereka tidak menetapkan tarif, tetapi
mengatakan : ”jika Bapak memiliki dana yang cukup jangan pelit, kalau tidak memadai,
kami siap menerima apa adanya.”
Penulis menduga, munculnya improvisasi
tentang masalah pengupahan baik dari para dai maupun orang-orang yang meminta dai untuk membimbing
mereka berawal
dari simpang siurnya pendapat para ulama mazhab tentang status upah dalam kerja
dakwah.
Perbedaan pendapat para Imam mazhab dan pengikutnya ini adalah
masalah yang
penting untuk diteliti. diharapkan akan menemukan
rumusan tentang konsep pengupahan yang seharusnya untuk para dai.
Mengingat mulianya kerja dakwah di dalam Islam dan strategisnya
peran dakwah
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta berangkat dari prinsip hidup
modern yang menuntut kerja secara profesional, maka saya menganggap penting
untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penulisan yang mendalam.
B.
Qurbah Sebagai Ciri
Khas Kerja Dakwah
Hukum pengupahan dalam bidang dakwah tidak
akan bisa dipahami tanpa didekati dengan kajian tentang qurbah, karena
bekerja di bidang dakwah masuk dalam wilayah ini. Menurut bahasa, qurbah didefinisikan
dengan danâ ( د ىّ ) yang berarti dekat sebagai lawan dari buʻd ( ثعد ) yang berarti jauh. Dari
sini kata kurban diambil. Menyembelih hewan disebut kurban karena perbuatan tersebut
diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[18]
Hampir sama dengan definisi menurut bahasa,
para ulama mendefinisikan qurbah dengan segala sesuatu yang dilakukan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta‟ala.[19]
Kata ‟segala sesuatu‟ mengisyaratkan bahwa qurbah mencakup semua hal, baik
pekerjaan tersebut memang bersifat qurbah seperti ibadah, atau muamalah seperti
bersedekah, maupun bukan untuk qurbah seperti membangun rumah, menjahit pakaian,
dsb, baik dilakukan oleh muslim maupun non muslim. Ungkapan ‟mendekatkan diri‟
mengisyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak untuk mendekatkan diri
tidak termasuk kategori qurbah. Sedangkan ungkapan ‟kepada Allah‟
mengisyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada
sesama makhluk atau untuk mendapatkan manfaat dunia tidak termasuk kategori qurbah.
Di antara ayat yang menjelaskan tentang kata qurbah adalah
QS. al-Taubah 99 dan QS. Al-Mā‟idah 27. QS. Al-Taubah 99 menampilkan pujian Allah
terhadap sikap
sebagian orang Arab Badui yang menginfaqkan hartanya dengan tujuan hanya untuk
mendekatkan dirinya kepada Allah. Sedangkan QS. Al-Mā‟idah 27 menjelaskan
tentang dua anak Adam, Habil dan Qabil, yang mempersembahkan hartanya
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Persembahan
Hâbîl diterima oleh Qâbîl tidak diterima karena yang diberikan adalah harta yang
paling tidak layak.[20]
Pembagian Qurbah
Untuk memahami qurbah secara mudah,
penulis mendekatinya dengan tiga kategori: pertama, pembagian qurbah berdasarkan
cakupan dan dampaknya; kedua, pembagian qurbah berdasarkan persyaratan
niat atau tidak; ketiga; pembagian qurbah berdasarkan hukum taklîfî.
1. Qurbah Berdasarkan Cakupan dan
Dampaknya
Dari segi cakupannya qurbah terbagi
dua, khaṣṣah (khusus) dan ʻammah (umum). Khaṣṣah adalah qurbah yang diwajibkan atau disunnahkan kepada seseorang
untuk melakukannya yang manfaatnya tidak dirasakan oleh orang lain,.
Contoh qurbah jenis ini adalah ibadah maḥḍah, seperti salat untuk dirinya, puasa, iktikaf untuk dirinya, haji untuk
dirinya, umrah untuk dirinya, zakat, qiyāmullail, ibadah-ibadah nawāfil yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya.[21]
Semua perkara yang wajib dilakukan oleh seseorang atau pekerjaan sunnah yang
dilakukan oleh seseorang karena pilihan yang manfaatnya kembali kepada pribadi
yang melakukannya dan tidak berdampak secara langsung kepada orang lain masuk
dalam kategori qurbah khaṣṣah (khusus).
Para ulama sepakat bahwa mengambil upah untuk pekerjaan yang
bersifat pribadi
dan dampaknya untuk dirinya sendiri hukumnya tidak boleh. Alasannya, karena
upah adalah pengganti dari jasa atau manfaat yang diberikan, padahal dalam kasus
di atas, tidak ada manfaat nyata dari pekerjaannya untuk orang lain.[22]
Contoh yang
nyata dari masalah ini adalah tidak mau melaksanakan salat kecuali diberi upah oleh
pihak lain; tidak mau iktikaf kecuali mendapatkan upah, dsb.
Adapun qurbah ʻammah (umum) adalah qurbah yang hasilnya tidak hanya dirasakan oleh
pelakunya tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Qurbah ʻammah ini dapat digolongkan dalam dua kelompok: pertama, manfaat qurbahnya
dirasakan oleh orang lain tetapi pelakunya tidak harus dari kalangan orang
Islam atau yang mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan
qurbah ini boleh dilakukan oleh orang kafir. Contoh
kelompok ini adalah mengajar baca tulis, mengajar berhitung, membangun
masjid, membangun jembatan, jalan, dan sebagainya.[23]
Untuk qurbah jenis ini, para ulama sepakat bahwa mengambil upah dari pekerjaan
ini hukumnya adalah boleh.[24]
Kedua, manfaat qurbahnya dirasakan oleh orang lain dan pelakunya harus
berasal dari kalangan muslim atau kalangan yang mendekatkan diri kepada Allah.
Contoh qurbah jenis ini adalah menjadi imam salat, menjadi muazin,
menjadi
khatib,
menjadi kadi, memberikan fatwa, mengajar Alquran, fiqh, hadis, ilmu-ilmu agama
secara umum, melakukan ḥisbah, dll. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat
apakah mengambil upah dari pekerjaan ini dibolehkan atau tidak.
2. Qurbah Berdasarkan Persyaratan Niat atau Tidak
Para ulama dari kalangan Mazhab Syafii membagi
qurbah berdasarkan persyaratan niat dalam dua kategori besar, yaitu:
pertama, qurbah yang tidak diterima kecuali dengan niat; dan kedua, qurbah
yang bisa diterima meskipun tidak dengan niat.
Qurbah yang tidak diterima
kecuali dengan niat terbagi lagi dalam dua bagian: qurbah
yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan qurbah yang bias digantikan
oleh orang lain. Adapun qurbah yang tidak bisa digantikan oleh orang
lain seperti
fardu ain yang mampu dilakukan sendiri, status hukum mengambil upah dari pekerjaan
seperti ini adalah tidak boleh. Sedangkan qurbah yang boleh digantikan oleh
orang lain seperti haji, orang yang mengerjakannya
boleh mengambil upah dari pekerjaan qurbah tersebut.
Sedangkan qurbah yang bisa diterima tanpa menghadirkan niat
juga terbagi dua; pertama fardu kifayah, dan kedua, qurbah syiar selain
fardu. Gambaran qurbah dari fardu kifayah adalah memandikan, mengafankan, dan menguburkan
mayit yang sebenarnya bukan kewajiban dirinya, karena dia tidak punya hubungan
langsung dengan
simayit dan bukan pula dari daerah tempat tinggal simayit, tetapi dia diminta oleh
pihak keluarga atau orang kampung asal simayit untuk melakukan pekerjaan qurbah
tersebut. Menurut Imam Nawawi, mengambil upah dari pekerjaan qurbah seperti
ini adalah boleh.[25]
Adapun qurbah syiar selain fardu seperti mengumandangkan
azan, status hukumnya menjadi perdebatan panjang para ulama. Hal ini akan
dibicarakan dalam kajian khusus. Qurbah berdasarkan
niat atau tidak juga sangat bermanfaat dalam disertasi ini, karena
sebagian amal qurbah boleh menerima upah dan sebagian yang lain tidak boleh
menerima karena faktor niat.
3. Qurbah Berdasarkan Hukum Taklīfī
Para ulama membagi qurbah berdasarkan hukum
taklīfī dalam lima perkara:1) Qurbah wajib; 2) Qurbah
mandūb; 3) Qurbah mubah; 4) Qurbah haram; 5) Qurbah
makruh.
Qurbah wajib adalah qurbah
yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap
Tuhannya, seperti salat, zakat, puasa dan haji. Qurbah inilah yang
disebut oleh
ulama dengan istilah qurbah maqṣūdah. Masuk dalam
kategori ini juga adalah qurbah yang diwajibkan
oleh seseorang terhadap dirinya, seperti nazar untuk salat tertentu,
puasa tertentu, melaksanakan haji selain yang wajib, dan nazar lainnya.
Qurbah mandūb meliputi semua hal yang dianjurkan oleh Islam untuk dilakukan seperti
salat-salat sunnah, puasa sunnah, haji lebih dari satu kali, sedekah, membaca
Alquran, wakaf, sedekah, silaturrahim, menjenguk orang sakit, melayat jenazah,
dll.
Qurbah mubah adalah semua pekerjaan yang boleh dilakukan,
tidak diwajibkan, tidak juga disunnahkan, boleh dikerjakan dan boleh
ditinggalkan. Hukum asal mubah tidak terkait dengan pahala atau dosa. Tetapi
pekerjaan mubah bias berubah menjadi mustaḥab (dianjurkan), atau wajib, atau haram, atau hukum lainnya karena niat orang
yang melakukannya. Contoh, makan makanan hukumnya mubah, tetapi kalau yang
makan niatnya untuk memperkuat diri agar mampu memenuhi perintah Allah maka
makan menjadi mustaḥab dan diberikan pahala.[26] Muʻadh
bin Jabal
menganggap bahwa bangun dan tidurnya adalah ibadah.
Qurbah haram adalah melakukan pekerjaan yang
mendekatkan diri kepada Allah tetapi dengan cara yang melanggar sunnatullah,
seperti berlebihan dalam ibadah, atau membebani diri dengan pekerjaan yang
tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama secara kontinyu. Seperti kisah
teguran Nabi kepada sahabatnya Utsman bin Maẓʻūn yang menghabiskan waktu
malamnya untuk salat dan waktu siangnya untuk puasa, bahkan menelantarkan
istrinya. Uthman bin Maẓʻûn menganggap hal itu sebagai qurbah, tetapi
dugaan itu ternyata ditepis oleh Rasul dan memerintahkan beliau untuk puasa dan
berbuka, salat malam dan juga tidur, karena keluarga punya hak, tamu punya hak,
dan diri juga punya hak. Di antara contoh qurbah haram adalah melakukan qurbah
di bidang harta, seperti wakaf, sedekah, hibah, padahal dia masih berhutang
atau memiliki tanggungan keluarga yang merupakan kewajibannya.
Sedangkan qurbah makruh adalah
melakukan qurbah secara berlebihan tetapi tidak mampu menjaga hatinya
atau melakukan hal-hal yang tidak prioritas dan meninggalkan hal-hal yang lebih
penting. Contoh, menyedekahkan semua harta yang dimiliki tetapi tidak sabar
hidup dengan kondisi apa adanya, atau mengeluarkan wasiat untuk orang miskin
padahal dia masih memiliki ahli waris yang membutuhkan.
Qurbah adalah di antara kajian sangat penting dalam
menentukan apakah pekerjaan yang masuk kategori ini -kategori untuk mendekatkan
diri kepada Allahbaik mutaʻaddiyah (dirasakan manfaatnya oleh orang lain) maupun
bukan, termasuk pekerjaan yang boleh dihargai dengan uang atau harta lainnya
ataukah pekerjaan ini adalah khusus untuk mengkhidmatkan diri kepada Sang
Pencipta, ataukah ada perbedaan antara qurbah yang mutaʻaddiyah dengan yang bukan, atau antara yang perlu niat dengan yang tidak atau
antara qurbah yang wajib, sunnah, boleh, makruh, dan haram?
Pertanyaan-pertanyaan di atas akan membantu
penulis membuat klasifikasi pekerjaan yang boleh mendapatkan upah dan pekerjaan
lain yang tidak boleh mendapatkan upah, atau klasifikasi ketiga, pekerjaan yang
boleh atau tidak boleh secara bersyarat.
Pekerjaan para dai secara umum masuk dalam wilayah qurbah. Karena
masuk dalam
wilayah ini, maka status mengambil upah dari kerja dakwah menjadi diperdebatkan.
Sebagian ulama berpendapat bahwa mengambil upah bertentangan dengan
keikhlasan, padahal amal qurbah ini adalah amal yang khusus diniatkan
untuk mendekatkan
diri kepada Allah.
Apakah semua jenis upah tidak diperbolehkan dalam kerja dakwah atau
ada jenis-jenis
upah yang mendapat toleransi? Pertanyaan ini akan dikaji dalam kajian di bawah
ini.
C. Hakikat Profesi dan Upah untuk Kerja Dakwah
Kerja profesi dalam tinjauan modern adalah
pekerjaan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dengan basis ilmu pengetahuan
dan keterampilan yang tinggi, dikerjakan dengan dedikasi yang baik, dan mereka
hidup dari pekerjaan tersebut.
Teori tentang profesi dalam tinjauan modern ini penulis anggap
penting diangkat
untuk menjajaki kemungkinan apakah dakwah layak dimasukkan ke dalam jajaran
profesi atau tidak menurut teori-teori di atas.
Kata yang tidak bisa dipisahkan dari profesi adalah profesional.
Jika profesi adalah pekerjaan, maka profesional adalah pekerjaan yang dikerjakan
dengan kualitas tinggi. Profesional selalu dikaitkan dengan profesi yang dikerjakan
dengan kepandaian
khusus dan dibayar sesuai dengan tingkat kepandaiannya.[27]
Jansen H.Sinamo (1958-...)[28]
mengatakan bahwa manusia profesional memiliki tujuh
mentalitas yang membedakannya dengan manusia lain. Ketujuh mentalitas itu adalah:
1) Mentalitas mutu. Dia berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam pekerjaannya.
2) Mentalitas altruistik. Dia melakukan hal itu dengan tujuan untuk memberikan
manfaat yang terbaik bagi orang lain. 3) Mentalitas melayani. Dia merasa
puas dengan pekerjaannya jika konstituen, pelanggan, atau pemakai jasa profesionalnya
telah terpuaskan lebih dahulu via interaksi kerja. 4) Mentalitas pembelajar.
Dia tidak boleh berhenti belajar untuk meningkatkan keahliannya. 5) Mentalitas
pengabdian. Dia sudah tidak berpikir untuk pindah ke profesi yang lain, dan
bekerja dengan sepenuh hati karena kecintaan dengan profesinya. 6) Mentalitas kreatif.
Dia tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi karena penghayatan atas pekerjaannya,
dia mampu melahirkan ide-ide baru dan segar di bidang profesinya. 7)
Mentalitas etis. Dia setia dengan kode etik profesinya, dan tidak akan mengorbankan
profesinya karena faktor materi.
Dengan tingkat kepandaiannya yang mumpuni
ditambah dengan mentalitas mereka yang tinggi, maka masyarakat sangat menaruh
kepercayaan tinggi terhadap mereka dan tidak mempercayakan pekerjaan itu kepada
orang lain.[29]
Konsekwensi logis dari bekerja yang professional adalah penghargaan
terhadap pekerja
dalam bentuk memberikan upah. Menurut Ibnu Manẓūr, ajr (upah) berarti imbalan
atas kerja.[30]
Dalam al-Muʻjam
al-Wasīṭ, ajr (upah)
adalah pengganti dari kerja dan jasa yang dikeluarkan. Al-Ajr al-haqq (upah yang
benar) diartikan sebagai imbalan yang
membuat pekerjanya tercukupi kebutuhannya untuk hidup tenang dan nyaman.
1. Upah dalam Pandangan Ulama Fiqh
Kajian tentang upah di dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadis dapat ditemukan
dalam kitab ijārah atau ijārāt atau kitab/ bab tentang sewa
menyewa. Sebagian ulama lain menggabungkan kajian tentang sewa menyewa
dengan kajian tentang jual beli (buyūʻ).
Berbagai ungkapan dikemukakan oleh para ulama fiqh ketika mendefinisikan kata
ijārah, tetapi semuanya bermuara kepada makna yang sama. Al-Sarkhasi
dari Mazhab Hanafî
mendefinisikan ijārah sebagai akad untuk mengambil manfaat dengan
penggantian.[31]
Al-Qarafi dari Mazhab Maliki mengatakan bahwa ijārah adalah menjual
manfaat.[32]
Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Imam Nawawi dari
Mazhab Syafii, dan Ibnu Qudâmah dari Mazhab Hambali.[33]
Memberikan upah
kepada manusia pada hakikatnya adalah membayar sewa kepada orang yang
bekerja atas pekerjaan yang dia lakukan. Para ulama membagi ijārah dalam dua kategori. Pertama, ijārah atas manfaat suatu barang; kedua, ijārah atas manfaat pekerjaan manusia.[34] Pada kategori
pertama (ijārah atas manfaat suatu barang), obyek yang diakadkan
adalah manfaat, seperti menyewakan rumah, ruko, kendaraan, pakaian, perhiasan,
bejana, dll. Manfaat yang bisa diambil dari orang
yang menyewa adalah dengan menempati, mengendarai, dan memakai. Rumah dan ruko
manfaatnya dengan ditempati, kendaraan bisa dikendarai. Pakaian, perhiasan, dan
bejana bisa dipakai.
Sedangkan ijārah atas manfaat pekerjaan manusia, obyek yang diakadkan adalah pekerjaan (ʻamal),
yaitu usaha yang dikerahkan oleh manusia untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan
penggantian upah tertentu. Seperti
membangun rumah, menjahit pakaian, mengantarkan seseorang ke tempat tertentu,
memperbaiki mobil, motor, dan kendaraan lainnya. Akad jenis kedua ini sangat
akrab dengan dunia profesi, di mana seorang yang berprofesi tertentu disewa oleh
seseorang yang memerlukan untuk memberikan manfaat kepadanya. Seperti seorang
insinyur bangunan
dikontrak untuk merancang gambar sebuah bangunan, seorang dokter dikontrak
untuk mengobati masyarakat yang sakit, dsb. Semua pegawai pemerintah, karyawan
di sebuah perusahaan, orang yang bekerja di lembaga-lembaga swasta, bekerja
sebagai pembantu rumah tangga, dan sebagainya masuk dalam kategori ijārah atas manfaat
pekerjaan manusia. Kajian tentang upah dai masuk dalam
kategori
kedua ini.
2. Al-Ijārah, al-Rizqu, al-Juʻlu, dan al-‘Aṭā’
Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan
pengupahan yang kadangkadang dipakai dalam makna yang sama, tetapi juga tidak
jarang dipakai untuk makna yang berbeda satu dengan lainnya. Kata-kata itu
adalah al-ijârah, al-rizqu, alju ʻlu, dan al-‘aṭā’. Kata
ijārah sudah dijelaskan pada sub tema sebelumnya. Penulis menganggap penting
untuk memaparkan
tiga istilah selain ijārah karena memiliki
relevansi yang kuat dengan penulisan ini.
Makna al-Rizqu
Al-rizqu menurut bahasa
berarti apa yang bisa dimanfaatkan.[35]
Secara umum, al-rizqu terbagi dua,
fisik dan non fisik. Al-Rizqu untuk fisik adalah hal-hal yang bermanfaat
untuk badan seperti makanan, sedangkan al-rizqu non fisik adalah yang bermanfaat
untuk hati dan jiwa, seperti ilmu dan wawasan.
Menurut istilah, al-rizqu didefinisikan
sebagai harta yang diberikan oleh pemerintah dari sumber baitulmal untuk
kemaslahatan kaum muslimin.[36]
Al-Jurjani mengatakan bahwa al-rizqu al-ḥasan adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang tanpa perjuangan yang susah
payah.[37]
Definisi yang menyatakan bahwa sumber al-rizqu harus berasal
dari sumber baitulmal seperti yang tersebut di atas ternyata tidak disepakati
oleh semua ulama. Ada yang mengatakan bahwa al-rizqu bisa bersumber dari
pribadi, atau lembaga sosial, atau dari sumber lain. Ibnu Qudāmah umpamanya, ketika
menjelaskan tentang sumber pendapatan seorang qadhi mengatakan bahwa apabila seorang
kadi tidak memiliki sumber penghasilan (al-rizqu), lalu dia mengatakan:
“aku tidak akan mengurus perkara ini sampai kalian berdua membayar uang perkara (al-rizqu) untukku.”
Menurut Ibnu Qudāmah, hal itu bisa dibolehkan dan bisa juga tidak.”
Kasus di atas menunjukkan bahwa kata „al-rizqu‟ tidak selalu
bersumber dari baitulmal, tapi bisa dari orang yang berperkara. Al-Ramli ketika
menjelaskan tentang hukum memberikan upah kepada muadzdzin mengatakan bahwa seorang warganegara
boleh memberikan al-rizqu (honor) dari
harta pribadinya untuk muazin.[38]
Perbedaan antara al-Ijārah dan al-Rizq
Ada ulama yang berpendapat bahwa al-rizqu digunakan untuk
makna yang berbeda dengan al-ijārah. Sedangkan
yang lain berpendapat bahwa al-rizqu kadangkadang dipakai
untuk makna yang sama dengan ijārah. Ulama yang
berpendapat bahwa dua kata ini berbeda mengatakan bahwa al-rizqu artinya
bantuan dari pemimpin yang diberikan kepada seseorang yang melaksanakan sesuatu
yang bermanfaat.
Al-rizqu bukan ʻiwaḍ (imbalan pengganti) dari kerja yang dilakukan.
Berdasarkan pendapat di atas, al- ijārah dan al-rizqu
bertemu pada makna memberikan dan mengeluarkan harta untuk memberikan penghargaan
kepada orang yang telah mendatangkan manfaat. Tetapi keduanya berbeda dalam
pendekatan motif pemberian. Al-rizqu diberikan dengan pendekatan kebaikan (iḥsān), sedangkan ijārah diberikan dengan pendekatan tukar menukar (muʻāwaḍah). Dari pos pengeluaranpun berbeda. Pemberian dalam bentuk al-rizqu ini
berasal dari pos baitulmal, sedangkan upah (ijārah) bersumber
dari siapa yang melakukan kontrak kerja dengan
pihak yang bekerja.
Tetapi Imam al-Mawardi menggunakan kata al-rizqu untuk makna
al-ijārah. Beliau
berpandangan bahwa al-rizqu tidak selalu diberikan dengan pendekatan pemberian,
tetapi juga bisa diberikan karena pendekatan tukar menukar. Kajian ini sangat
relevan ketika mengkaji pengupahan dai. Pos
pendapatan mana yang paling memungkinkan untuk diberikan kepada dai? Ternyata,
para ulama tidak berbeda pendapat untuk memberikan al-rizqu kepada imam
masjid, tetapi mereka berbeda pendapat kalau memberikan upah kepada mereka dengan menggunakan
akad ijārah.[39]
Perbedaan pendapat ini akan dikaji dalam bab empat.
Makna al-Juʻlu
Al-Juʻlu adalah juʻālah atau jiʻālah adalah janji yang diucapkan oleh orang yang sudah baligh
dan berakal untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada orang yang
melakukan pekerjaan tertentu apakah orang yang melakukannya itu tertentu atau
tidak tertentu, dan orang yang berjanji memberikan harta wajib memenuhi
janjinya jika orang yang dijanjikan telah merealisasikan pekerjaan yang telah
ditetapkan olehnya.[40]
Seperti memberikan upah kepada dokter dengan syarat kesembuhan, dan memberikan
upah kepada guru dengan syarat yang diajar menjadi pintar.[41]
Al-juʻlu dan ijārah bertemu pada kepastian upah. Artinya, pada saat akad dibuat,
harus disebutkan besaran upah yang akan diberikan apabila pekerjaan yang tertera
dalam akad selesai dilakukan. Tetapi al-juʻlu berbeda dengan ijārah dalam tiga
aspek: pertama, kebolehan melakukan akad untuk pekerjaan yang tidak pasti70; kedua,
al-juʻlu tidak diberikan kecuali setelah pekerjaan yang disebutkan dalam klausul
perjanjian telah dilaksanakan. Sedangkan ijārah boleh diberikan
dengan cicilan;
ketiga, ijārah berstatus wajib dengan terjadinya aqad, sedangkan al-ju‟lu tidak
wajib diberikan kecuali setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
Hukum bolehnya akad juʻālah ini didasari
oleh Alquran dan Sunnah. Dasar dari Alquran adalah kisah Nabi Yusuf yang mengatakan kepada
saudara-saudaranya bahwa pihak kerajaan kehilangan piala raja, dan dia menjamin akan
memberikan makanan seberat beban unta bagi siapa yang dapat mengembalikannya.
Sedangkan dari sunnah adalah cerita dari Abu Saʻid al-Khudri tentang beberapa
sahabat Nabi yang sedang mendatangi sebuah perkampungan. Ternyata mereka tidak
diterima dengan
baik oleh penduduk kampung. Dalam kondisi seperti itu, ternyata pemuka desa
tersebut tersengat oleh binatang dan akhirnya mereka meminta tolong kepada para
sahabat Nabi untuk mengobati pemuka mereka. Para sahabat menolak untuk mengobati
pemuka kampung tersebut kecuali jika penduduk kampung mau menjamu dan
memberikan sesuatu kepada mereka. Akhirnya mereka memberikan daging kambing
kepada para sahabat. Lalu salah seorang sahabat mengobati pemuka kampung
itu dengan membacakan al-Fatihah dan mengumpulkan air ludah lalu meludahkannya
kepada pemuka kampung tersebut. Ternyata dia sembuh dan menghadiahkan
seekor kambing kepadanya. Para sahabat ragu untuk memakan hasil pengobatan
itu sehingga bertanya tentang status hukumnya kepada Rasulullah. Ternyata
Rasulullah tertawa dan bahkan meminta bagian dari daging kambing tersebut.
Baik dalil Alquran maupun Sunnah secara jelas
menyebutkan tentang akad untuk memberikan sesuatu kepada orang yang bisa
melakukan pekerjaan yang belum jelas tingkat kesuksesannya.
Makna al-‘Aṭa’
Para ulama menggunakan istilah ‘aṭa’ untuk dua hal. Ada yang menggunakannya
untuk pengganti materi yang diberikan oleh negara kepada orang yang
telah melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. Pernyataan Imam al- Mawardi
tentang kewajiban negara memberikan gaji kepada pasukan perang menggunakan
terminologi „aṭa‟.
Ulama lain menggunakan istilah ‘aṭa’ untuk pemberian jaminan sosial yang diberikan negara kepada warganya yang
berhak untuk menerimanya. Umar bin Abdul Aziz ketika menulis surat kepada Abdul
Hamid bin Abdurrahman- gubernurnya di Irak- tentang perintah mengeluarkan
jaminan social kepada masyarakat dari baitulmal, beliau menggunakan kata uʻṭiyah yang merupakan jama‟
dari ‘aṭa’. Ketika semua orang yang berhak menerima jaminan sosial sudah menerimanya,
ternyata sisa anggaran di baitulmal masih ada. Gubernurpun menulis surat
kembali kepada khalifah tentang sisa anggaran yang ada. Khalifah memerintahkan
beliau untuk mencari data orang yang memiliki hutang, jejaka yang ingin
menikah, dan orang yang berat untuk membayar jizyah agar dibantu. Empat
bentuk kompensasi di atas sangat berharga dalam penulisan ini, agar kompensasi
yang diberikan kepada dai dapat dipertimbangkan secara akurat.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
besar di atas dirinci dalam poin-poin kesimpulan di bawah ini:
1. Karena dakwah
memiliki ciri khas sebagai amal qurbah yang orang biasa melakukannya karena ingin mendekatkan
diri kepada Allah dan hanya mengharapkan
pahala dari Allah, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum menerima upah dari kerja dakwah
antara boleh dengan tidak boleh. Perdebatan
tersebut diakibatkan oleh perbedaan cara memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah ini serta
perubahan situasi dan kondisi pada saat fatwa dikeluarkan.
2. Kelayakan kerja dakwah masuk ke dalam jajaran profesi
seperti kerja profesi lainnya penulis ambil setelah semua syarat-syarat
profesionalitas bisa diterapkan untuk kerja dakwah meskipun ada kekhasan yang
tidak dimiliki oleh profesi lainnya, yaitu tentang sifat dakwah yang di dalam
Islam masuk dalam kategori amal qurbah. Syarat-syarat utama profesi
adalah masalah keilmuan, lembaga yang menopang berkembangnya keilmuan, wadah
yang menaungi para lulusan, kode etik dan masalah upah sebagai konsekwensi dari
profesionalitas.
3. Pendapat penulis tentang bolehnya mengambil upah dari
kerja dakwah tidak sejalan dengan pendapat Imam Hanifah dan Mazhab Hanafi Mutaqaddimīn,
seperti Abu Yusuf dan Muhammad yang melarang dai untuk mengambil upah dari
kerja dakwahnya. Pendapat penulis juga tidak sejalan
dengan pandangan Albāni yang sama
sekali tidak membolehkan dai mengambil upah dari dakwah atas nama ujrah. Penulis setuju dengan pendapat Imam
Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad dengan
kekuatan dalil yang mereka kemukakan. Meskipun penulis menganggap untuk saat sekarang pendapat Abu Hanifah
dan ulama awal Hanafiyyah tidak relevan
lagi, tetapi penulis sangat menghargai pendapat ini, karena fatwa ini keluar dalam rangka menjaga izzah para dai dan
agar orang-orang yang bergelut dalam profesi
ini tidak berubah niatnya hanya untuk mengejar keuntungan dunia.
Tentang keharusan memperhatikan ekonomi dai agar hidup
dalam tingkat ekonomi yang baik tidak sejalan dengan pandangan skeptis Ibnu
Khaldun tentang nasib ekonomi orang-orang yang memilih terjun ke dunia dakwah. Pandangan
beliau berangkat dari perspektif hukum permintaan dan penawaran. Menurut beliau,
karena dakwah bukan kebutuhan ḍarūrah (primer)
maka permintaannya tidak banyak, dan karena permintaan tidak banyak, maka
pemasukan menjadi tidak besar. Berdasarkan data-data historis yang diungkapkan oleh
Ahmad Shalabi, penulis lebih setuju dengan pendapat Ahmad Shalabi yang
mengatakan bahwa tidak selamanya dai hidup dalam taraf ekonomi yang rendah,
tetapi sebagian mereka mendapatkan penghargaan yang tinggi baik dari pemerintah
maupun dari masyarakat.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
D. Hendropuspito, O.C, Sosiologi Agama (Jakarta: Penerbit
Kanisisus, 1983)
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama, Sebuah Pengantar (Bandung:
Mizan, 2005),
Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, al-
Muqaddimah (Beirut: Al-Maktabah Al- „Aṣriyyah, 1420-2000), cet. 2,
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourses (U.K.
and U.S, Everyman‟s Library, 1979),
_____________________; Perihal
Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik, (Jakarta: Penerbit Dian
Rakyat, 1989, cet.1, Alih Bahasa, Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat).
Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi (Jakarta: Tintamas,
1970), cet. 2.
Ibnu Man ūr, Lisān al-ʻArab, (Beirut: Dār Ṣādir,1412-1992), juz. 14, h.30.
Onong
Uchjana Effendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 248.
Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Tugas Penyuluh Agama Islam (Jakarta,
2007), h.11.
Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah
(Beirut: Al-Maktabah al- „Aṣriyyah, 1420-2000), cet.2.
Ahmad Syalabi, Tārīkh al- Tarbiyah al-Islāmiyyah (Kairo: Dār al-Ittiḥād al-‟Arabi li al-Ṭibāʻah, 1976),
Abu Jaʻfar Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin
Salamah al-Azdi al Ṭahāwi, Sharḥ Maʻāni al-Ătsār,
Ibnu Maudūd al- Mūṣilī, al-Ikhtiyār li Taʻlīl al -Mukhtār, juz 1,
Malik
bin Anas, al -Mudawwanah (Beirut: Dār al- Kutub al- ʻIlmiyyah, , 1415- 1994), juz 1,
Imam al-Nawawi, Al Majmūʻ Sharḥ al-Muhadhdhab (Beirut: Dār Iḥya‟ al -Turāth al – „Arabi,1422-2001),
, juz 3, cet.1,
Majalah Harkat, Vol. 1-No.7, 7 Desember 2001.
Abu al-Ḥusain Ahmad Ibnu Fāris, Muʻjam Maqāyīs al-lughah (Beirut: Dār al-Jalīl, 1411), cet.1, ,
Ibnu ʻĀbidīn, Ḥāshiyah Radd al-Mukhtār ‘ala al-Durr al- Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār, yang dikenal dengan nama Ḥāshiyah Ibnu Ābidīn (Beirut: Dār al-Fikr, 1421-2000),
Abu ʻAbdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubi
al-Anṣāri, Al Jāmiʻ li Aḥkām Alquran ( Beirut: Dàr al-Kutub al-‟Ilmiyyah, 1408-1988),
Abu Jaʻfar al-Ṭabari, Tafsīr Jāmiʻ al-Bayān fî Ta’wīl al-Quran, yang dikenal dengan Tafsīr al-Ṭabari (Muassasah al-Risālah, 1420 -2000),.
Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarkhasi, Al-Mabsūṭ, (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1409),
Ibnu Qudāmah, al-Mughni,
Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu
Taimiyah,, Majmūʻ al-Fatāwā (Rubāṭ, Maghrib: Maktabah al-Maʻārif, t.th),
Alā‟uddin Abu Bakar bin Masʻud,Al-Kāsāni, Badā’iʻ al-Ṣanā’iʻ fî Tartīb al Sharā’iʻ, (Beirut : Muassasah al-Tārīkh al-„Arabī, 1421 H),
Muḥyiddin bin Sharaf al- Nawawi, , Rauḍat al- Ṭālibīn wa Umdat al –Muftīn (Beirut: Al- Maktab al-Islāmi, 1412), cet.3,
Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar, al-Wāḍiḥ fî Uṣūl al-Fiqh (ʻAmmān: Dār al- Nafā-is,1428), cet. 4, h. 44.
Syafruddin
Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Ciputat
Pers),
George
Ritzer, Encyclopedia of Social Theory ( London: Sage Publications, Inc,
2004),
Shihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarâfi, Al-Dzakhīrah (Beirut: Dār al-Gharbi, 1994),
Ibnu ʻÃbidîn, Hāshiyah Radd al-Mukhtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār (Beirut: Dār al- Fikr, 1421-2000),
Muhammad bin Idris al-Syafii al-Umm, (Beirut: Dār
al- Kutub al- ʻIlmiyyah, 1415-1994),
Al-Fairuz Ābādi, al-Qāmūs al-Muhīṭ, bab Qāf, Faṣl Rā‟ (Beirut: Dār Ihyā‟
al-Turāts al- „Arabiy, 1991), cet. 1,
Ahmad bin ʻAli bin Hajar al -„Asqalāni, Fatḥ al-Bāri, (Kairo: Dār al-Bayān Li al- Turāts, 1409-1988),
Al-Jurjani, al-Taʻrīfāt, (Kairo: Percetakan Musṭafa al-Bâbi al-Ḥalabi,
1357 H)
Shihābuddīn Muhammad bin Abu al-ʻAbbās al-Ramli, Nihāyat al-Muḥtāj ila Sharḥ al- Minhāj (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1414 H),
Al-Mawardi, al-Ḥāwi al-Kabīr (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994), cet. 1,
Ibnu Ḥajar, Tuḥfat al-Muḥtâj (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994), cet.1,
Ibnu Rushd, Bidāyat al-mujtahid wa Nihāyat al-muqtaṣid, (Beirut: Dār Ihya‟ al-Turāth al- „Arabiy, 1992), cet.1,
[1] D.
Hendropuspito, O.C, Sosiologi Agama (Jakarta: Penerbit Kanisisus, 1983)
h.38-
[2] Jalaluddin
Rakhmat, Psikologi Agama, Sebuah Pengantar (Bandung: Mizan, 2005), h.39.
[3] Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, al- Muqaddimah (Beirut:
Al-Maktabah Al- „Aṣriyyah, 1420-2000), cet. 2, h. 124.
[4] Jean-Jacques
Rousseau, The Social Contract and Discourses (U.K. and U.S, Everyman‟s
Library, 1979), h. 271; Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum
Politik, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1989, cet.1, h. 118. Alih Bahasa,
Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat).
[5] Mohammad
Hatta, Sekitar Proklamasi (Jakarta: Tintamas, 1970), cet. 2, h. 66-71.
[6] Muballigh
berasal dari kata ballagha, artinya ablagha. Ablagha adalah
menyampaikan
pesan
kepada orang lain hingga pesan itu benar-benar sampai. (Majmaʻ al-Lughah
al-ʻArabiyyah, Al-
Muʻjam al-Wasît , Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah), h. 69.
[7] Uswah
berasal dari kata usa, artinya yang bisa dijadikan teladan (qudwah).
(Ibnu Man ūr,
Lisān al-ʻArab, (Beirut: Dār Ṣādir,1412-1992),
juz. 14, h.30.
[8]
Gabriel Tarde dari Perancis adalah salah seorang yang berpengaruh dalam ilmu
komunikasi
gaya
Amerika. Teori imitasi adalah bagaimana seseorang dipengaruhi oleh perilaku
orang lain yang
berinteraksi
sehari-hari. Onong Uchjana Effendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Jakarta:
PT.
Citra Aditya Bakti, 2003), h. 248.
[9]
Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Tugas Penyuluh
Agama
Islam (Jakarta,
2007), h.11.
[10] Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah
(Beirut: Al-Maktabah al- „Aṣriyyah, 1420-2000), cet.2. h. 364. Tidak
semua sepakat dengan teori Ibnu Khaldun tentang kecilnya sumber pendapatan orang-orang yang bekerja di bidang agama. Ahmad
Syalabi mengatakan bahwa tidak semua
pendapat orang-orang yang bekerja di bidang agama mendapatkan penghasilan yang
kecil tetapi sebagian
mereka hidup dalm taraf ekonomi yang cukup tinggi. (Ahmad Syalabi, Tārīkh
al- Tarbiyah al-Islāmiyyah
(Kairo: Dār al-Ittiḥād al-‟Arabi li al-Ṭibāʻah, 1976), juz 4, h.
237.
memberikan manfaat. (Al-Jurjani, al-Taʻrīfāt, juz 1, h.1).
dilakukannya. (Al-Jauhari, al-Ṣiḥāḥ fi-al-lughah, juz 1, h.94).
Maʻāni al-Ătsār, juz 5, h.129.
[15]
Lihat, Malik bin Anas, al -Mudawwanah (Beirut: Dār al- Kutub al-
ʻIlmiyyah, , 1415-
1994), juz 1, h. 121.
„Arabi,1422-2001), , juz 3, cet.1,
h. 93-94.
[17] Majalah Harkat,
Vol. 1-No.7, 7 Desember 2001.
[18] Abu al-Ḥusain Ahmad Ibnu Fāris, Muʻjam Maqāyīs al-lughah (Beirut: Dār al-Jalīl, 1411), cet.1, juz 5, h. 80-81;
Ibnu Manẓūr, Lisān al-ʻArab (Beirut: Dār Ṣādir,1412-1992), juz 1, h. 662.
[19] Ibnu ʻĀbidīn, Ḥāshiyah Radd al-Mukhtār ‘ala al-Durr al- Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār, yang dikenal dengan nama Ḥāshiyah Ibnu Ābidīn (Beirut: Dār al-Fikr, 1421-2000), juz 1 h. 272; Lihat juga, Abu ʻAbdillah
Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubi al-Anṣāri, Al Jāmiʻ li Aḥkām Alquran ( Beirut: Dàr al-Kutub al-‟Ilmiyyah, 1408-1988), juz 4,
h. 296.
[20] Abu Jaʻfar al-Ṭabari, Tafsīr Jāmiʻ al-Bayān fî Ta’wīl al-Quran, yang dikenal dengan Tafsīr al-Ṭabari (Muassasah al-Risālah, 1420 -2000), juz 10, h. 202.
[21] Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarkhasi, Al-Mabsūṭ, (Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1409), juz 4 h. 158.
[22] Ibnu Qudāmah, al-Mughni,
juz 8 h. 141.
[23] Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu
Taimiyah,, Majmūʻ al-Fatāwā (Rubāṭ, Maghrib: Maktabah al-Maʻārif, t.th),
juz 30 h. 206.
[24] Alā‟uddin Abu Bakar bin Masʻud,Al-Kāsāni, Badā’iʻ al-Ṣanā’iʻ fî Tartīb al Sharā’iʻ, (Beirut : Muassasah al-Tārīkh al-„Arabī, 1421 H), Badā’iʻ al-Ṣanâ’i, juz 4, h. 191-192.
[25] Muḥyiddin bin Sharaf al- Nawawi, , Rauḍat al- Ṭālibīn wa Umdat al –Muftīn (Beirut: Al- Maktab al-Islāmi, 1412), cet.3, juz 5, h.187.
Nafā-is,1428), cet. 4, h. 44.
[27]
Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta:
Ciputat Pers),
h.18.
[28]
Jansen H.Sinamo adalah penggagas, pencipta, pengembang, sekaligus pengemban
„pelatihan sumberdaya
manusia berbasis etos yang pertama di Indonesia. Bersama Andrias Harefa, pada
1998 ia juga mendirikan
Institut Darma Mahardika, lembaga pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia dan organisasi berdasarkan etos kerja profesional.
[29]
George Ritzer, Encyclopedia of Social Theory ( London: Sage
Publications, Inc, 2004), h.
603.
[32] Shihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarâfi, Al-Dzakhīrah (Beirut: Dār al-Gharbi, 1994), juz 5, h. 371.
[33] Ibnu Qudāmah, al-Mughni,
juz 11, h.371.
[34] Ibnu ʻÃbidîn, Hāshiyah Radd al-Mukhtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār (Beirut: Dār al- Fikr, 1421-2000), juz 6, h. 4; Muhammad bin Idris
al-Syafii al-Umm, (Beirut: Dār al- Kutub al-
ʻIlmiyyah, 1415-1994), juz 3, h. 250.
[35] Al-Fairuz Ābādi, al-Qāmūs al-Muhīṭ, bab Qāf, Faṣl Rā‟ (Beirut: Dār Ihyā‟
al-Turāts al- „Arabiy, 1991), cet. 1, juz 3 h. 343.
[36] Ahmad bin ʻAli bin Hajar al -„Asqalāni, Fatḥ al-Bāri, (Kairo: Dār al-Bayān Li al- Turāts, 1409-1988), juz 13, h. 160.
[38] Shihābuddīn Muhammad bin Abu al-ʻAbbās
al-Ramli, Nihāyat al-Muḥtāj ila Sharḥ al- Minhāj (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1414 H), juz 1, h. 418.
[39] Al-Mawardi, al-Ḥāwi al-Kabīr (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994), cet. 1, jilid 16 h. 246.
[40] Ibnu Ḥajar, Tuḥfat al-Muḥtâj (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994), cet.1, jilid 7, h. 497.
[41] Ibnu Rushd, Bidāyat al-mujtahid wa Nihāyat al-muqtaṣid, (Beirut: Dār Ihya‟ al-Turāth al- „Arabiy, 1992), cet.1, jilid 2, h.301.
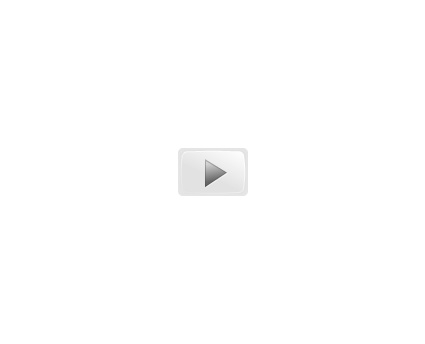
Tidak ada komentar:
Posting Komentar